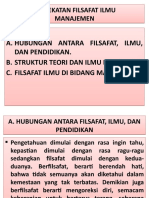Professional Documents
Culture Documents
Face Negotiation Muted Group
Uploaded by
LeliLynnOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Face Negotiation Muted Group
Uploaded by
LeliLynnCopyright:
Available Formats
TEORI NEGOSIASI MUKA (FACE NEGOTIATION THEORY) DAN TEORI KELOMPOK BUNGKAM (MUTED GROUP THEORY)
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teori Komunikasi Disusun oleh :
Widi Tri Setyaningsari Rosalina Karisma Indahwati Medianti Laksinta Leli Ristawati Evi Dianti Ahmad Zul Fahmi
F1C009088 F1C010037 F1C010044 F1C010045 F1C010048 F1C010065 F1C010075
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO 2011
Face Negotiation Theory
A. Pencetus dan Latar Belakang Teori Negosiasi Muka adalah satu dari sedikit teori yang secara ekspilist mengakui bahwa orang dari budaya yang berbeda memiliki bermacam pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran inilah yang menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda. Ting-Toomey mendasarkan banyak bagian dari teorinya pada muka dan facework. Muka jelas merupakan fitur yang penting dalam kehidupan, sebuah metafora bagi citra diri yang diyakini David Ho (1976) melingkupi seluruh aspek kehidupan sosial. Konsep muka telah berevolusi dalam hal interpretasi selama bertahun-tahun. Konsep ini bermua dari bangsa Cina, yang sebagaimana dikemukakan oleh Ho, memiliki konseptualisasi mengenai muka: lien dan mien-tzu, dua istilah yang mendeskripsikan identitas dan ego. Ho mengamati bahwa muka (face) adalah citra diri yang ditunjukkan orang dalam percakapannya dengan orang lain. Ting-Toomey dan koleganya (Oetzel, Yokochi, Masumoto dan Takai, 2000) mengamati bahwa muka berkaitan dengan nilai diri yang positif dan/atau memproyeksikan nilai lain dalam situasi interpersonal.
B. Asumsi Teori Asumsi dari teori face negotiation theory adalah, melalui adanya perbedaan yang terjadi dalam tiap budaya atau kelompok, dalam komunikasi yang terjadi, terkadang ada proses penyampaian pesan yang tidak tersampaikan sehingga menimbulkan miss communication atau salah pengertian di dalam kelompok tersebut. Sebuah budaya akan memiliki adat, kebiasaan, nilai, norma, dan hal lain yang mengikat yang mengidentifikasi mereka menjadi sebuah budaya tersebut. Konflik akan muncul saat dua kelompok atau lebih memiliki perbedaan dan tidak bisa menerima identitas dari kelompok lain. Dalam Em. Griffin, Ting-Toomey mengasumsikan bahwa setiap orang dalam tiap budaya akan selalu menegosiasikan atau merundingkan identitas mereka (face). Istilah ini mengacu pada pencitraan diri, cara kita meminta orang lain agar melihat keberadaan kita dan berprilaku menyenangkan terhadap kita. Maka dari hal ini muncullah istilah facework, yang berarti penyampaian pesan verbal dan nonverbal yang dikemukakan secara spesifik yang akan membantu menjaga dan memperbaiki wajah
yang kalah atau saat posisi terlihat lebih rendah dan berusaha untuk memperoleh wajah yang penuh dengan penghargaan (Em. Griffin, 2004:435) Secara garis besar Face Negotiation Theory memiliki 3 asumsi yang pada intinya terdiri dari konsep kunci teori ini, yaitu wajah, konflik dan budaya: 1. Self identity is important in interpersonal interactions, with individuals negotiating their identities differently across culture. Identitas diri merupakan sesuatu hal yang penting penting di dalam interaksi interpersonal. Namun dalam interaksinya, individuindividu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda sesuai dengan budaya asal mereka. Melekat dengan asumsi pertama adalah keyakinan bahwa para individu di dalam semua budaya memiliki beberapa citra diri yang berbeda dan bahwa mereka menegosiasikan citra ini secara terus-menerus. Dalam banyak budaya yang berbeda, orang-orang membawa citra yang mereka presentasikan kepada orang lain secara kebiasaan atau strategis. TingToomey percaya bahwa bagaimana kita memersepsikan rasa akan diri kita dan bagaimana kita ingin orang lain untuk memersepsikan kita merupakan hal yang sangat penting dalam pengalaman komunikasi kita 2. The management of conflict is mediated by face and culture. Konflik merupakan peristiwa yang dapat merusak dan menyebabkan kerenggangan antar orang yang semula berhubungan sangat dekat. Dalam konteks ini, konflik yang terjadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan wajah dan budaya. Hal ini dikarenakan (sama seperti yang telah disebutkan di atas) cara seseorang menghadapi dan meyelesaikan konflik sangat berhubungan erat dengan cara bagaimana ia dibesarkan. Atau dengan kata lain, orang yang dibesarkan dalam kebudayaan barat memiliki cara mengatasi konflik yang berbeda dengan orang yang dibesarkan dalam kebudayaan timur. Menurut Ting-Toomey, konflik dapat merusak muka sosial seseorang dan dapat mengurangi kedekatan hubungan antara dua orang. Sebagaimana ia nyatakan, konflik adalah forum bagi kehilangan muka dan penghinaan terhadap muka. Konflik mengancam muka kedua pihak dan ketika terdapat negosiasi yang tidak bersesuaian dalam bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Contohnya, dalam budaya Amerika, menganggap bahwa
menunjukkan perbedaan di antara dua orang sebagai hal yang penting, sementara budaya lain yakin bahwa konflik harus ditangani secara diamdiam 3. Certain acts threaten ones projected self-image (face) Asumsi ketiga berkaitan dengan dampak yang dapat diakibatkan oleh suatu tindakan terhadap muka. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menampilkan beraneka macam ekspresi. Menurut asumsi ini, terdapat dua pola dalam face threatening process yaitu face saving & face restoration. Face saving merupakan usaha untuk mencegah terjadinya sesuatu yang memalukan sedangkan face restoration merupakan strategi yang
dilakukan untuk melindungi otonomi atas diri sendiri dan mencegah jatuhnya harga diri karena malu.
C. Aplikasi Teori Teori ini menyediakan dasar-dasar untuk memprediksi bagaimana individu mengaplikasikan facework dalam budaya yang berbeda. Konsep face dalam teori ini mengacu pada citra diri seseorang di hadapan orang lain, yang mencakup soal rasa hormat, status, hubungan, loyalti, dan nilai-nilai serupa. Dengan kata lain, face berarti rasa nyaman seseorang tentang dirinya dalam keadaan apa pun yang dipreskripsikan oleh budayanya. Facework adalah perilaku komunikasi yang kita gunakan untuk membangun dan melindungi muka kita sekaligus untuk melindungi, membangun, atau bahkan menghancurkan face orang lain (membuat orang lain kehilangan muka). Misalnya, saat kita melihat orang sedang memamerkan hartanya, itu adalah satu bentuk facework. Saat facework itu ditampilkan, kita bisa menganalisis atau membaca, sebenarnya facework itu ditujukan pada dirinya sendiri atau pada pendengan langsungnya, atau untuk menyindir orang ketiga yang tak terlibat dialog tapi bisa mendengar pembicaraannya. Istilah sederhananya adalah, saat orang menyombongkan dirinya, saat itulah terjadi facework. Suatu citra diri yang ingin diampilkan si pelaku agar orang lain memandang mukanya.
D. Kritik Terhadap Teori Hal yang menarik, teori negosiasi muka telah menerima beberapa klarifikasi dari Ting-Tooney sendiri, dan hal ini mendorong terjadinya perbaikan teori. Terkadang,
dimensi budaya ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perbedaan budaya. Dalam penelitiannya sendiri, Ting-Tooney dan koleganya menemukan beberapa ketidaksesuaian. Ia menemukan bahwa responden Jepang menunjukkan lebih banyak perhatian terhadap muka diri dibandingkan responden Amerika Serikat. Selain itu walaupun Ting-Tooney mengemukan bahwa budaya individualistik biasanya tidak berkompromi dalam gaya konflik mereka, responden Amerika Serikat yang sangat individualistik menggunakan tingkat berkompromi yang tinggi secara signifikan ketika dihadapkan dengan konflik. Dalam hal ini identitas aku dari responden Amerika Serikat tidak malah tampak. Isu isu tambahan seputar konsistensi logis masih tetap ada. Maksudnya isu isu lain berkaitan dengan kepedulian akan muka yang masih belum ditemukan para peneliti masih tetap ada. Penerapan dan integrasi dari penelitian mengenai kesantunan yang dilakukan Ting-Tooney mungkin harus direfleksikan dan dipertimbangkan lebih lanjut.
Muted Group Theory
A. Pencetus dan Latar Belakang Teori Sudah sejak dulu, para ahli antropologi berusaha untuk memahami budaya dengan melakukan penelitian lapangan dan menulis etnografi. Melalui cara kerja yang dilakukan para antropolog tersebut diharapkan sebuah budaya akan dapat dideskripsikan dengan detail, komplet dan akurat. Para pertengahan tahun 1970, dua orang antripolog, Edwin Ardener (1975) seorang antropologis sosial dari Oxford University dan Shirley Ardener (1978) sebagai rekan kerjanya menunjukan minat untuk melihat cara kerja para antropolog budaya tersebut di lapangan. Mereka melihat bahwa ternyata para antropolog melakukan penelitiannya dengan lebih banyak berbicara dan bertanya kepada kalangan laki-laki dewasa pada suatu budaya tertentu untuk kemudian mencatatnya dalam etnografi sebagai gambaran budaya secara keseluruhan. Sehingga tidak seluruh porsi dari deskripsi budaya tersebut, seperti perempuan, anak-anak dan posisi dari pihak yang tak berdaya lainnya, disajikan sebagai bagian dari cerita budaya tersebut. Edwin Ardener dalam monografinya, Kepercayaan dan Problem Perempuan mengemukakan kecenderungan aneh di kalangan etnografer yang mengklaim harus memecahkan kode dari sebuah budaya tanpa membuat refensi langsung pada setengah masyarakat yang terdiri dari kalangan perempuan. Para peneliti lapangan seringkali membenarkan kelalaian tersebut dengan melaporkan betapa sulitnya menggunakan perempuan sebagai informan budayanya. Hal ini disebabkan karena bahasa yang digunakan oleh perempuan bersifat rapport talk, yaitu cenderung berbicara untuk membangun keakraban dan membutuhkan penerimaan orang lain dalam berbahasa dan banyak berbasa-basi, sehingga bagi para etnografer hal itu dianggap menyulitkan mereka. Sementara itu, bahasa yang digunakan oleh laki-laki labih bersifat report talk, yang cenderung hanya untuk memberikan penjelasan dan tidak dalam rangka membangun keakraban dan hal ini justru memudahkan etnografer untuk memperoleh banyak penjelasan dari kalangan laki-laki. Ardener awalnya berasumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan adalah sebuah masalah gender yang unik pada antropologi sosial. Tetapi hal ini kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh rekan kerjannya, Shirley Ardener yang menyadari bahwa kebungkaman kelompok yang kurang kekuasaan menimpa kelompok-kelompok yang menempati tempat yang paling akhir dari tingkat
masyarakat. Orang-orang yang hanya memiliki kekuasaan yang rendah bermasalah dengan persoalan menyuarakan persepsi-persepsi mereka. Ardener mengatakan bahwa struktur kebungkaman mereka ada tetapi tidak bisa dicapai dari struktur bahasa dominan. Hasilnya adalah mereka dipandang rendah, diredam dan dibuat tak tampak sebagaimana lubang hitam belaka dalam alam orang lain. Edwin Ardener membuktikan bahwa fenomena pembungkaman tersebut memiliki dua segi. Pertama, para peneliti antropologi (yang biasanya orang kulit putih) tidak mendengarkan suara-suara dari kalangan yang tidak berdaya (powerless), karena mereka biasa menyimak dari kalangan laki-laki dan mendengarkan bahasa laki-laki mereka tidak mencari atau memahami suara-suara dari kalangan perempuan dalam proses penelitiannya. Peremuan dalam hal ini dipandang sebagai pihak yang sukar berbicara oleh para penelitidan Edwin Ardener menyatakan bahwa jika lakilaki ditampilkan pandai berbicara dibandingkan dengan perempuan ini adalah sebuah kasus dari yang suka berbicara kepada yang suka. Kedua, diluar masalah ketulian pihak laki-laki kalangan perempuan sengaja dibungkam selama penelitian. Shirley Ardener melihat proses ini sebagai kejadian overtime. Kata-kata yang secara kontinyu menyerang telinga yang tuli, tentu akhirnya menjadi tidak diucapkan. Siklus ketulian dan kebisuan ini dipergunakan sebagai basis untuk muted group theory. Melalui pengamatan yang mendalam oleh Ardener, tampaklah bahwa bahasa dari suatu budaya memiliki bias laki-laki yang inheren didalamnya, yaitu bahwa lakilaki menciptakan makna bagi suatu kelompok, dan bahwa suatu perempuan ditindas dan dibungkam. Perempuan yang dibungkam ini dalam pengamatan Ardener, membawa kepada ketidakmampuan perempuan untuk dengan lantang
mengekspresikan dirinya dalam dunia yang didominasi laki-laki. Muted group theory ini kemudian dikembangkan secara lebih lengkap oleh Cheris Kramarae dan koleganya. Kramarae adalah profesor speech communication dan sosiolog di Universutas Illinois. Dia juga profesor tamu di pusat studi perempuan (Center For The Study Of Women) di Universitas Oregon dan baru-baru ini sebagai dekan di Universitas Perempuan Internasional (The International Womans University) di Jerman. Dia memulai karier penelitiannya pada tahun 1974 ketika dia memimpin sebuah studi sistematik mengenai cara-cara perempuan dilukiskan dalam kartun. Kramarae menemukan bahwa perempuan dalam kartun biasanya dilukiskan sebagai emosional, apologetik (peminta maaf/penyesal) dan plin-plan sedangkan pernyataan yang sederhana dan kuat disuarakan oleh laki-laki.
Teori ini telah difasihkan terutama sebagai teori feminis, dengan perempuan sebagai kelompok yang dibungkamkan, tetapi bisa juga diterapkan pada kelompok budaya terpinggirkan lainnya. Sebagaimana dijelaskan Orbe (1998), Di dalam masyarakat yang memelihara hubungan kekuasaan yang asimetris, kerangka kelompok yang dibungkam berada. Dalam lingkup komunikasi, teori ini termasuk konteks kultural yang mengkaji gender dan komunikasi dan salah satu dari teori kritis. Cheris Kramarac sendiri menyatakan bahwa bahasa itu benar-benar sebuah konstruksi yang dibuat oleh laki-laki. Bahasa sebagai bagian dari budaya tidak digunakan semua pembicara secara sama, karena tidak semua pembicara berkontruksi pada cara formulasi yang sama. Perempuan (dan anggota kelompok subordinat lainnya) tidak bebas atau tidak semampu laki-laki untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, kapan dan dimana mereka inginkan, karena kata-kata dan norma yang mereka gunakan telah diformulasi oleh kelompok laki-laki yang dominan (Griffin, 2003:487). Oleh karena itu, kata-kata yang digunakan kalangan perempuan dipotong dan pemikiran perempuan juga dievaluasi (diturunkan nilainya) dalam masyarakat kita. Ketika perempuan mencoba untuk mengatasi ketidakadilan ini, kontrol komunikasi yang maskulin menempatkan mereka pada kerugian yang sangat besar. Bahasa yang dibuat laki-laki menjadi alat dalam mendefinisikan, menurunkan dan meniadakan keberadaan perempuan, sehingga perempuan pun menjadi kelompok yang dibungkam. Teori ini memandang bahwa bahasa adalah batasan budaya, dan karenanya laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, laki-laki lebih mempengaruhi bahasa sehingga menghasilkan bahasa laki-laki. Hal ini terjadi, karena bahasa dari budaya yang khusus tidak menyajikan semua pembicara (speakers) secara sama, tidak semua pembicara berkontribusi dalam formulasi cara yang sama. Perempuan (dan anggota dari kelompok subordinat) tidak sebebas dan semampu laki-laki untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, kapan, dan di mana, karena kata-kata dan norma untuknya menggunakan formulasi dari kelompok dominan, yaitu laki-laki.
B. Asumsi Teori Kramarae (1981) merancang tiga asumsi yang terpusat pada sajian feminisnya dari muted group theory yaitu :
1. Perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki karena perempuan dan laki-laki memiliki pangalaman yang sangat berbeda. Pengalaman yang berbeda ini berakar pada divisi kerja masyarakat. 2. Karena laki-laki merupakan kelompok yang dominan di masyarakat, sistem persepsi mereka juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. 3. Sehingga agar berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi modelnya dalam term sistem ekspresi yang dominan tersebut. Muted group theory melalui konsep persepsi ini membawa proses komunikasi pada garis terdepan. Khususnya muted group theory mengemukakan bahwa karena kelompok dominan (khususnya laki-laki kulit putih Eropa) mengontrol makna ekspresi publik seperti pada kamus media, hukum dan pemerintah maka gaya ekspresi mereka mempunyai hak istimewa (privileged). Sokongan komunikasi laki-laki kulit putih ini akan memasukkan segala sesuatu dari perspektif dominasi rasionalitas publik dan organisasional yang berbicara dengan menggunakan metafora untuk memberikan komentar dan lelucon yang menghina perempuan. Kramare (dalam Miller, 2002: 293) juga mengembangkan tujuh hipotesis mengenai Muted group theory yaitu 1. Perempuan kemungkinan besar lebih sulit mengekspresikan diri mereka sendiri dalam caracara ekspresi publik yang dominan dibandingkan lakilaki 2. Laki-laki lebih sulit dari pada perempuan dalam mengenai makna anggota dari gender lain 3. Perempuan kemungkinan akan menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka sendiri di luar cara-cara ekspresi publik dominan yang digunakan laki-laki dalam konvensi verbal maupun perilaku nonverbal mereka 4. Perempuan kemungkinan besar labih menyatakan ketidakpuasan pada cara-cara ekspresi publik dominan laki-laki 5. Perempuan menolak untuk hidup dengan gagasan-gagasan dari organisasi sosial yang ditangani oleh kelompok dominan dan akan mengubah caracara ekspresi publik dominan karena mereka secara sadar dan secaraverbal menolak gagasan tersebut
6. Perempuan tidak seperti laki-laki dalam menciptakan kata-kata ynag diakui secara luas dan digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Konsekuensinya perempuan merasa tidak dianggap berkontribusi terhadap perkembangan bahasa 7. Selera humor perempuan akan berbeda dari selera laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki konseptualisasi dan ekspresi yang berbeda, sehingga sesuatu yang tampak lucu bagi laki-laki menjadi sama sekali tidak lucu bagi perempuan Muted group theory merupakan teori yang menarik dari teori komunikasi kritis dan termasuk dalam konteks kultural yang membahas mengenai gender dan komunikasi. Teori ini memusatkan perhatiannya pada kelompok tertentu dalam masyarakat yang mengungkap struktur-struktur penting yang menyebabkan
penindasan dan memberikan arah bagi perubahan yang positif.
C. Aplikasi Teori Muted group theory sendiri banyak menitik beratkan terhadap gender, dimana suara wanita dinilai lebih lemah. Pemikiran kaum wanita tidak dinilai sama sekali. Dan ketika kaum wanita coba menyuarakan ketidaksetaraan ini, kontrol komunikasi yang dikuasai oleh paham maskulin cenderung tidak menguntungkan para wanita. Dan bahasa yang diciptakan oleh kaum pria diciptakan dengan berpretensi, tidak menghargai dan meniadakan kaum wanita. Wanita oleh karenanya menjadi kelompok yang terbungkam (muted group). Shirley Ardener kemudian mengingatkan bahwa muted group theory tidak melulu menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan terbungkam selalu berarti tidak bersuara. Kelompok yang terbungkam tidak berarti mereka tidak bersuara sama sekali atau terdiam. Ketika seseorang mengubah apa-apa yang mereka ingin katakan hanya agar tidak merasa dikucilkan oleh lingkungan sosialnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam kelompok yang terbungkam. Contoh yang paling mudah adalah dalam hal menyatakan perasaan. Seorang wanita tidak sebebas dan memiliki akses yang luas sebagaimana kaum pria dalam mengekspresikan apa yang mereka inginkan, kapan, dan di mana mereka menginginkannya, karena kata-kata dan norma-norma yang digunakan pada dasarnya dibentuk oleh kelompok dominan, yaitu kaum pria itu sendiri. Sering kita temui ketika seorang pria mencintai lawan jenisnya, maka pria tersebut bisa dengan bebas
menyatakan perasaannya. Lain hal dengan wanita, ketika mereka ingin menyatakan perasaannya kepada seorang pria yang Ia suka atau cinta, maka wanita akan sulit menyatakan perasaannya. Karena lingkungannya akan menilai hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh wanita. Contoh lain dalam dunia politik, suara wanita akan kurang di hargai karena pria menilai wanita lebih cocok bekerja di dapur, mengurus kebutuhan rumah tangga. Sehingga suara wanita akan kurang di dengar oleh publik, karena dinilai suara wanita dan suara pria dinilai berbeda derajatnya.
D. Kritik Terhadap Teori 1. Penganiayaan Perempuan yang berlebihan. Teori ini dikiritik karena terlalu menekankan pada masalah aniaya terhadap perempuan. 2. Ketidaktepatan politis. Teori ini bertujuan politis karena teori ini digunakan untuk kemajuan agenda politik dalam pemberian kuasa pada kalangan perempuan. Dan teoretisi kelompok yang dibungkam ini akan sepakat bahwa mereka melakukan agenda politik dengan melakukan perubahan konstruktif dalam masyarakat dengan mengurangi ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Para teoretisi tersebut tidak melihat masalah dengan menghadirkan nilai dalam sebuah teori. Dalam opini mereka, nilai melekat pada semua teori, meskipun teori konvensional menyangkal nilai yang ada dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, ilmuwan kritis membantah, taori tentang kehidupan sosial harus didasarkan pada nilai dan harus berusaha memperbaiki masyarakat. 3. Tidak realistik. Kritik final terhadap teori kelompok yang dibungkam adalah bahwa hal itu utopia. Tidak unik bagi teori ini karena telah dilontarkan pada teori kritis secara umum (Blumler, 1983; Real, 1984). Klaim kritis menyatakan teori-teori kritis secara umum dan teori kleompok yang dibungkam sebagai baginnya, terlalu idealistis dalam meyakini bahwa perubahan yang mereka inginkan dapat terealisasi. Menurut beberapa orang yang was-was mengenai teori kritis, perubahan yang meluas tidak mungkin karena keberadaan ketidakadilan harus diakui dan diakomodasi. Barangkali hal itu utopia dalam mengkhayalkan membuat lagi bahasa termasuk ekspresi dan perspektif perempuan.(Wood, 2004: 272-273).
Daftar Pustaka
Griffin, Emory A. 2003, A First Look at Communication Theory, 5th edition, New York Richard West & Lynn Turner. 2008, Pengantar Ilmu Komunikasi, Analisis dan Aplikasi, Edisi 3, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta (Terjemahan dari: Introducing Communication Theory : Analisys and Aplication, tahun 2007) Sendjaja, S. Djuarsa, 2002. Teori Komunikasi, Cetakan 1, Universitas Terbuka, Jakarta
FN Teori negosiasi muka berasumsi bahwa orang dari berbagai budaya memiliki perhatian terhadap presentasi muka mereka. Teori ini merupakan teori yang mencampurkan konflik kedalam kerangkanya, dan menjelaskan mengapa anggotaanggota dari dua budaya yang berbeda, misalnya mengelola konflik secara berbeda. Ting-Tooney menyatakan bahwa nilai-nilai budaya yang berbeda terdapat didalam menghadapi konflik, dan episode-konflik yang dipenuhi dengan konflik ini, sebagai gantinya juga dipengaruhi oleh kepedulian akan muka dan kebutuhan akan muka dari komunikasi. ... Ada dua jenis facework: preventive dan restorative. Konsep jaim dalam bahasa gaul kan facework preventif.preventive facework adalah facework yang kita gunakan untuk melindungi diri kita dari ancaman terhadap face kita. Misalnya, saat mau nembak cewek, supaya nanti kalo ditembak gak malu, kita bilang gini: "gua cuma mau ngungkapin perasaan, tapi gua gak maksa elo nerima kok, gua gak desperate butuh pacaran banget, cuma ngungkapin perasaan aja....". Atau contoh lain misalnya ada orang yang nanya soal sesuatu. nah, begitu dikasih penjelasan, dia akan bilang:" wah, cuma gitu doank? kalo gitu sih gw juga tahu...." Dia ngomong gitu supaya gak terlihat inferior di hadapan pemberi info. Padahal, pada saat bersamaan, dia bisa kehilangan face itu Restorative facework diaplikasikan untuk membangun kembali face seseorang setelah face itu jatuh. misalnya setelah kita bersikap memalukan, kita akan bilang: "gw gak biasanya begitu. itu tadi bukan diri gw yang sebenarnya...." ... Kritik : ga selamanya perbedaan budaya jadi pemicu berbedanya cara penilaian seseorang terhadap yang lain. Kembali pada karakter masing-masing pribadi. -----------------------------------------------------MG Sebenarnya pembungkaman thd prp itu perlu ato ga?
You might also like
- Teori Negosiasi MukaDocument30 pagesTeori Negosiasi Mukafhiqy asjuwitaNo ratings yet
- Teorii Negosiasi Wajah UasDocument16 pagesTeorii Negosiasi Wajah UasBenaya prabowoNo ratings yet
- Face Negotiation TheoryDocument20 pagesFace Negotiation TheoryRani NaniboNo ratings yet
- MAKALAH Negosiasi WajahDocument10 pagesMAKALAH Negosiasi WajahYakinNo ratings yet
- Teori Negosiasi MukaDocument21 pagesTeori Negosiasi Mukafhiqy asjuwitaNo ratings yet
- Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Gaya HidupDocument8 pagesPengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Gaya HidupGugum GumilarNo ratings yet
- Mengembangkan Keterampilan Komunikasi Lintas BudayaDocument2 pagesMengembangkan Keterampilan Komunikasi Lintas BudayauNo ratings yet
- Cognitive Dissonance TheoryDocument11 pagesCognitive Dissonance Theorythereshyakenzela kenzela100% (1)
- DramatismDocument7 pagesDramatismAtika Tri Harini IsaNo ratings yet
- KepribadianDocument31 pagesKepribadianMuhamad Sultan AgungNo ratings yet
- Frankfurt School Awalnya Berasal Dari Pemikiran Dari Mazhab FrankfurtDocument2 pagesFrankfurt School Awalnya Berasal Dari Pemikiran Dari Mazhab FrankfurtZahra LatifahNo ratings yet
- Pentingnya Strategi Komunikasi Dalam PerusahaanDocument7 pagesPentingnya Strategi Komunikasi Dalam Perusahaanfadi_parkerNo ratings yet
- Sejarah IntelektualDocument38 pagesSejarah IntelektualYoseph F BugaNo ratings yet
- Representasi Kecantikan Wanita Dalam Film 200 Pounds Beauty PDFDocument13 pagesRepresentasi Kecantikan Wanita Dalam Film 200 Pounds Beauty PDFMeldina ArianiNo ratings yet
- Aplikasi Dan Manfaat Knowledge ManagementDocument9 pagesAplikasi Dan Manfaat Knowledge ManagementMila SmartNo ratings yet
- Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang MasalahDocument21 pagesBab I Pendahuluan A. Latar Belakang MasalahWinda_Pandeiro_5703No ratings yet
- Teori Budaya Organisasi &criticalDocument12 pagesTeori Budaya Organisasi &criticalSalman HasibuanNo ratings yet
- KERTAS KERJA Kilang BiskutDocument7 pagesKERTAS KERJA Kilang BiskutNaimahFadhilahNo ratings yet
- Teori Agenda SettingDocument6 pagesTeori Agenda SettingMuhammad AS Siddiq100% (1)
- Pendekatan Filsafat Ilmu ManajemenDocument35 pagesPendekatan Filsafat Ilmu Manajemendanar adhiNo ratings yet
- Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan DakwahDocument42 pagesStrategi Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan DakwahFathiyyah AzamNo ratings yet
- Konsep Dasar Komunikasi OrganisasiDocument10 pagesKonsep Dasar Komunikasi OrganisasiAkinari TatsunoNo ratings yet
- Agama Islam - Kelompok 3 - 1D3A - Aqidah, Ibadah, Akhlak, MuamalahDocument18 pagesAgama Islam - Kelompok 3 - 1D3A - Aqidah, Ibadah, Akhlak, MuamalahFAZLY QAIS FEBRIYANTO mhsD3KL2020RNo ratings yet
- Al-Quran Dan Al-Hadis SDMDocument15 pagesAl-Quran Dan Al-Hadis SDMNur SakinahNo ratings yet
- Hubungan Filsafat Dengan IlmuDocument11 pagesHubungan Filsafat Dengan IlmuRizki TikaNo ratings yet
- Komunikasi Antar BudayaDocument17 pagesKomunikasi Antar BudayaDhell DhelaaNo ratings yet
- Jurnal KuantitatifDocument13 pagesJurnal Kuantitatifrizal efendiNo ratings yet
- Spiral of SilenceDocument19 pagesSpiral of SilenceImel Civil UnimedNo ratings yet
- Semiotika Visual MakalahDocument17 pagesSemiotika Visual MakalahAlif AbyadlulNo ratings yet
- Tugas AldoDocument10 pagesTugas AldoAldoNo ratings yet
- Persepsi, Kognisi, Dan EmosiDocument14 pagesPersepsi, Kognisi, Dan EmosiAde RahayuNo ratings yet
- KURIKULUM Menurut FrobelDocument15 pagesKURIKULUM Menurut FrobelAdella Rahma LinaNo ratings yet
- Bab 5 Syarat Penentu BeritaDocument6 pagesBab 5 Syarat Penentu BeritaIndiani Risma PutriNo ratings yet
- TMK 1 - Filsafat Dan Etika KomunikasiDocument2 pagesTMK 1 - Filsafat Dan Etika KomunikasiGhufron GhiffariNo ratings yet
- Presentasi DramaturgiDocument17 pagesPresentasi DramaturgiHenrikus Hendriko RajagukgukNo ratings yet
- Mengambil KeputusanDocument11 pagesMengambil KeputusanBrama Gamz DjabarNo ratings yet
- Peran Orang Tua PWGDocument22 pagesPeran Orang Tua PWGYohanes Hidaci AritonangNo ratings yet
- Komponen Komunikasi PesanDocument3 pagesKomponen Komunikasi PesanTitisan YoutubeNo ratings yet
- Teori Negosiasi MukaDocument21 pagesTeori Negosiasi MukaZuzu FinusNo ratings yet
- Komunikasi Antar Budaya Kelompok 1Document14 pagesKomunikasi Antar Budaya Kelompok 1Muhamad JefriiNo ratings yet
- Power DistanceDocument9 pagesPower DistancediahhhNo ratings yet
- Eksploitasi Dan Alienasi Buruh Pabrik (Studi Deskriptif Buruh Pabrik Aluminium Di Kawasan Jalan Medan-Binjai Km. 12)Document193 pagesEksploitasi Dan Alienasi Buruh Pabrik (Studi Deskriptif Buruh Pabrik Aluminium Di Kawasan Jalan Medan-Binjai Km. 12)NIRWANNo ratings yet
- Teori Peluru Atau Jarum SuntikDocument19 pagesTeori Peluru Atau Jarum SuntikUñà Piñky SiTépuNo ratings yet
- Contoh Perbaikan Kalimat Tidak EfektifDocument2 pagesContoh Perbaikan Kalimat Tidak EfektifNurfi AprilNo ratings yet
- HiperealitasDocument3 pagesHiperealitasOrochimaru Sampun TobatNo ratings yet
- Azaz-Azaz Manajemen MakalahDocument16 pagesAzaz-Azaz Manajemen MakalahIrna WahyuniNo ratings yet
- Edward Burnett TaylorDocument8 pagesEdward Burnett TaylorAndi AnnaNo ratings yet
- Review8 Raden Ahmad Rosyiddin Brillyanto 11171110000024 AgamaDocument2 pagesReview8 Raden Ahmad Rosyiddin Brillyanto 11171110000024 AgamaAhmad RosyiddinNo ratings yet
- Kelompok 2 - Konvergensi MediaDocument64 pagesKelompok 2 - Konvergensi MediaChansoo 29No ratings yet
- Perkembangan OrganisasiDocument7 pagesPerkembangan OrganisasiOka P LestariNo ratings yet
- Teori Konvergensi SimbolikDocument3 pagesTeori Konvergensi SimbolikStephen HarrisNo ratings yet
- Proses Komunikasi MassaDocument2 pagesProses Komunikasi Massanelsonsotarduga0% (1)
- Penelitian Komunikasi Antar BudayaDocument18 pagesPenelitian Komunikasi Antar BudayaBarbara RossNo ratings yet
- Laporan KKN Desa Cicareuh 2023Document43 pagesLaporan KKN Desa Cicareuh 2023aka seraNo ratings yet
- Analisis Pengelolaan PT Gojek Indonesia Dalam Bingkai Teori Tradisional Dan ModernDocument13 pagesAnalisis Pengelolaan PT Gojek Indonesia Dalam Bingkai Teori Tradisional Dan ModernArie SabelaNo ratings yet
- Tugas Spiral of SilenceDocument7 pagesTugas Spiral of SilenceBagusNo ratings yet
- Teori Negosiasi MukaDocument5 pagesTeori Negosiasi MukaRahmat AbdillahNo ratings yet
- Teori Negosiasi MukaDocument4 pagesTeori Negosiasi MukaFebrian PeppytoNo ratings yet
- Face Negotiation TheoryDocument3 pagesFace Negotiation TheorymargarethalelyanaNo ratings yet
- Kepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaFrom EverandKepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)