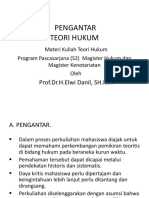Professional Documents
Culture Documents
TEORI KRIMINOLOGI POSMODERNolehProfMustofa PDF
Uploaded by
Amal Bahri100%(9)100% found this document useful (9 votes)
4K views17 pagesOriginal Title
TEORI_KRIMINOLOGI_POSMODERNolehProfMustofa.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
100%(9)100% found this document useful (9 votes)
4K views17 pagesTEORI KRIMINOLOGI POSMODERNolehProfMustofa PDF
Uploaded by
Amal BahriCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 17
1
TEORI KRIMINOLOGI POSMODERN
Muhammad Mustofa
I. Pendahuluan
Pemikiran-pemikiran kriminologi dalam bentuk teori akan selalu berkembang sesuai dengan
perkembangan sosial, dan dengan cara bagaimana manusia memaknai dunia (sosial) tempat ia hidup.
Ketika manusia dalam kehidupannya telah mencapai tahapan modern, yang awalnya ditandai oleh
pemikiran-pemikiran ilmiah paduan antara rasio dengan realitas empiris, sikap ilmiah tersebut
menjadikan ilmuwan bersikap kritis dan skeptis terhadap pengetahuan (teori) yang sudah ada dan
berusaha memperoleh pemahaman lebih lengkap tentang dunia sosial tempat ia hidup. Ternyata
modernitas yang berkembang sejak abad 17 sampai dengan abad 20 tidak membuat manusia hidup
lebih bahagia dan sejahtera. Masyarakat modern ditandai oleh adanya ketertiban, keseragaman,
rutinitas, efisiensi, rasionalitas, terrencana, dapat diramalkan, yang berdampak pada kehidupan sosial
yang monoton. Dalam keadaan seperti itu, manusia modern mempertanyakan makna kehidupan setelah
mencapai tahap modern, mengalami kekosongan makna hidup, karena ternyata modernitas
menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan. Pengaruh perkembangan teknologi informasi hasil kecerdasan
manusia mempengaruhi interkasi sosial yang merupakan ciri dari manusia.Interaksi sosial tidak lagi
dilakukan secara tatap muka tetapi secara elektronik. Dunia nyata berubah menjadi dunia maya
(virtual). Kekosongan nilai hidup inilah yang antara lain mendorong munculnya pertanyaan, setelah kita
menjadi modern (posmodern), kita mau menjadi seperti apa?
Konsep posmodern pertamakali digunakan dalam dunia arsitektur. Para arsitek muda merasa
kreatifitasnya dibatasi oleh pakem-pakem geometri Pitagoras yang serba teratur dalam wujud garis
lurus dan garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Karya arsitektur yang pada dasarnya
merupakan karya seni dibatasi oleh pakem-pakem geometri konvensional tersebut. Banyak arsitek muda
yang memberontak dengan pakem-pakem konvesnional tersebut dan merancang bangunan tidak lagi
terikat dengan pakem-pakem lama. Mereka membuat disain bangunan yang "semau gue" sesuai dengan
dorongan kesenimanan mereka. Mereka tidak lagi terikat dengan struktur geometeris konvensional,
garis lurus dan lengkung beraturan tetapi disain garis sesuai dengan jiwa keseniannya.
Ditinggalkannya pola-pola konvensional dalam menjalankan ilmu tersebut mempengaruhi pola berfikir
bidang-bidang ilmu lain termasuk ilmu sosial dan kriminologi di dalamnya. Pemikiran posmodern
memikirkan ulang hakikat ilmu dan mengevaluasi seberapa jauh ilmu pengetahuan ilmiah (teori)
memberi manfaat bagi kehidupan manusia (abad ke 21). Kriminologi posmodern yang pada hakikatnya
merupakan perkembangan pemikiran kritis, melakukan otokritik terhadap pemikiran kriminologi kritis
yang mempolitisasi kejahatan dan tidak memberi manfaat bagi kebaikan struktur sosial.
Pemikiran posmodern, sebagaimana lajimnya setiap pemikiran ilmiah, dipengaruhi oleh pemikiran-
pemikiran sebelumnya. Dalam hal ini pemikiran posmodern dipengaruhi oleh pemikiran Perancis akhir
1960-an dan awal 1970-an, yang kecewa terhadap pemikiran kritis konvensional, bertransisi dari
Hegelian ke Nitzshenean. Selain itu juga melandaskan diri pada pemikiran Deleuze, Guattari, Derrida,
Lyotard, Baudrillard, Foucault, Kristeva dll. Pemikir utama posmodern adalah para pemikir feminisme
seperti Irigaray, Moi, dan Cious. Yang merupakan tokoh utama alternatif pemikiran tentang subyek,
dampak menentukan dari wacana, hakikat keteraturan simbolik adalah Jacques Lacan. Gelombang
pemikiran yang baru cenderung merumuskan pemikirannya berdasarkan teori chaos, teorem Godel,
teori katastrof, mekanisme kuantum, dan teori topologi. Dirumuskan dan dikembangkan terus-menerus
konsep-konsep baru tentang ruang, waktu, subyektivitas, peran wacana, kehendak (desire), struktur
2
sosial, peran, perubahan sosial, pengetahuan, dan hakikat kerusakan (harm), keadilan, dan hukum.
Menganjurkan untuk meninggalkan suatu pusat, hak-hak khusus titik referensi, subyek yang tetap, asas-
asas pertama, dan asal usul (Sarup, 1989:59 sebagaimana dikutip Milovanovic, 1997:hlm 2). Lihat juga
uraian populer oleh Glenn Ward (2003) "postmodernism" dalam serial buku "teach yourself".
Kriminologi posmodern secara epistemologis mempertanyakan ulang tentang hakikat manusia,
masyarakat dan struktur sosial, peran-peran, subyektivitas/agensi-agensi, wacana, pengetahuan,
ruang/waktu, kausalitas, dan perubahan sosial. Terkait dengan itu, semua teori kriminologi yang ada
harus ditulis ulang disesuaikan dengan pemaknaan baru hakikat yang dipertanyakan secara
epistemologis oleh pemikiran posmodern. Dalam aplikasinya, para pemikir posmodern kriminologi
melakukan:
1. pendefinisian ulang konsep kejahatan dan memperluas tema-tema penelitian kriminologi;
2. menyusun teori;
3. merekomendasikan langkah-langkah konkrit dalam pengendalian kejahatan.
Bahan ajar ini akan membahas krimnologi posmodern dalam tiga langkah konkrit yang dilakukan
tersebut di atas.
II. Pendefinisian Ulang Konsep Kejahatan.
Dalam bagian ini akan dibahas:
1. Kriminologi realis.
2. Kriminologi feminisme
3. Piramida dan prisma kejahatan sebagai alat ukur.
4. Hate crime.
5. Chatastropic criminology.
6. Topological representation of criminal event.
II.1. Kriminologi realis.
Kriminologi realis muncul sebagai reaksi terhadap kriminologi kritis yang mendahuluinya khususnya
terhadap gagasan filosofis dan politiknya yang mengabaikan dampak dari kejahatan jalanan terhadap
korbannya, serta mengusulkan alternatif-alternatif dalam kebijakan pengendalian kejahatan. Kriminologi
realis mempunyai perhatian khusus pada realitas akibat dari tindakan kejahatan konvensional yaitu
timbulnya korban kejahatan yang bersifat khusus, dan timbulnya rasa takut terhadap kejahatan.
Berdasarkan pemahaman terhadap survai korban kejahatan, diketahui bahwa yang paling menderita
sebagai akibat dari kejahatan konvensional adalah perempuan. Oleh karena itu kriminologi feminis
memprotes bahwa kejahatan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan adalah sesuatu yang
sungguh-sungguh terjadi secara siginifikan dan tidak ada hubungannya dengan definisi kejahatan oleh
penguasa. Sedangkan penjelasan tentang rasa takut terhadap kejahatan bukanlah sesuatu yang tidak
rasional dan keta-khayulan, dan penelitian ilmiah tentang viktimisasi dan penyimpangan perempuan
tidak merupakan ancaman politik. Selain perempuan, kelompok-kelompok yang cenderung men-jadi
korban kejahatan adalah orang berkulit berwarna, maupun kelas pekerja (Rock, 1992). Kriminologi realis
inilah yang mendorong pemikiran kriminologi feminis yang memperjuangkan perlindungan perempuan
dalam masyarakat maupun dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didorong oleh data survai korban
3
bahwa kaum perempuan merupakan mayoritas dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus
yang menyangkut perempuan tersebut dalam proses peradilan pidana diperlakukan sebagai kasus rata-
rata seperti kejahatan yang lain, dan mengabaikan realitas bahwa korbannya adalah perem-puan yang
secara struktural diposisikan sebagai pihak yang lemah.
Perkembangan pemikiran kriminologi realis (kiri) dipicu oleh pemikiran Young pada tahun 1979, tokoh
kriminologi kritis, yang mengemukakan konsep idealisme kiri yang melihat masalah kejahatan sebagai
memerlukan ideologi penafsiran ulang terhadap sejarah dan pembentukan masyarakat yang baru.
Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri realisme bukan pada dekonstruksi maupun rekonstruksi
konsep hukum dan ketertiban, tetapi mempersoalkan masalah kejahatan sekarang dalam konteks
tempat yang bersifal lokal. Karena perhatian utama kriminologi adalah kejahatan, maka secara progresif
memerlukan pengalaman, pencegahan, dan pengen-dalian kejahatan untuk kepentingan kelompok
berdasarkan kelas, gender, ras, etnisitas, seksualitas, ideologi dan sebagai-nya yang merupakan korban-
korban ketertiban kapitalis. Terkait dengan hal itu maka menurut Lea dan Young (1984:359-363),
terdapat enam pokok manifesto dari kriminologi realisme yaitu:
1. Kejahatan sungguh-sungguh merupakan masalah.
2. Kita harus melihat pada realitas di balik kemunculannya.
3. Kita harus mengendalikan kejahatan secara serius.
4. Kita harus melihat secara realistis keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pelanggar
maupun kor-bannya.
5. Kita harus realistis dalam pemolisian.
6. Kita harus realistis tentang masalah kejahatan pada masa sekarang ini.
Pandangan kriminologi realis tentang kejahatan tersebut dan pengendaliannya didasarkan pada
penelitian survai korban yang bersifat lokal. Sebagai contoh, tokoh realis Jock Young dalam Realist
Research as a Basis for Local Criminal Justice Policy (Young, 1992: 33-72) berpendapat bahwa tingkat
kejahatan adalah hasil dari bekerjanya empat faktor yaitu : (1) polisi dan agen-agen pengendalian sosial
yang lain, (2) publik, (3) pelaku pelanggaran, (4) korban. Dalam pemikiran realis, menganalisa kejahatan
harus bersifat khusus, yaitu tentang kejahatan tertentu dan tentang pemolisian yang tertentu pula, dan
tidak berdasarkan gambaran rata-rata. Asas dalam analisa ini dalam pemikiran realis dijadikan aksioma
yang tidak dapat ditawar-tawar. Realisme memberikan perhatikan khusus pada ketidaksetaraan
distribusi kejahatan menurut usia, ras, dan gender. Young mengkritik hasil penelitian survai korban yang
bersifat nasional yang cenderung mengatakan bahwa ketakutan terhadap kejahatan bersifat tidak
rasional. Menurut Young ketakutan terhadap kejahatan yang dialami oleh perempuan adalah respon
yang rasional tidak hanya terhadap viktimisasi kriminal, tetapi juga terhadap berbagai bentuk pelecehan
dan tindakan yang tidak-beradab yang tidak akan dialami oleh laki-laki.
Meskipun realisme melandaskan diri pada empirisme namun realisme lebih merupakan bentuk integrasi
antara observasi dengan teori, dan mengedepankan etiologi daripada kesempatan. Oleh karena itu
realisme mempertimbangkan kembali pemahaman sebab-musabab kejahatan yang merupa-kan ciri
kriminologi modern (positivis), namun tanpa ambisi generalisasi dan hubungan sebab-akibat tidak
dipandang sebagai hubungan linear tetapi hubungan trajektori. Dalam kaitan ini, Young berpendapat
bahwa kejahatan yang terjadi di pusat kota dapat dijelaskan sebagai tingkah laku rasional yang berakar
pada masalah materi.
Dalam rangka pengendalian kejahatan, survai korban di lokasi yang tertentu dapat dijadikan masukan
dalam merancang kebijakan pengendalian kejahatan dan pemolisian yang sesuai dengan kebutuhan
4
korban. Proses mengolah masukan menjadi kebijakan, menurut Young meliputi empat tahapan, yaitu :
(1) identifikasi permasalahan, (2) penilaian prioritas, (3) aplikasi dari asas-asas, dan (4) pertimbangan
kemungkinan-kemung-kinan. Dalam tataran praktis, dengan demikian realisme mempromosikan agar
supaya masyarakat dapat meng-artikulasikan permasalahannya sendiri dan bukan menurut pandangan
orang lain. Melalui cara ini akan dapat ditengarai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
pengendalian sosial kejahatan.
II.2. Kriminologi Feminisme
Kriminologi feminisme berkembang sebagai kritik atas kecenderungan tahun 1970-an (lihat Muncie,
McLughlin, Langan, 1997:xxii) yang banyak menghasilkan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan
oleh perempuan, yang dikritik sebagai bias gender, karena memandang perempuan yang melanggar
hukum sebagai penyimpang ganda, pertama karena ia perempuan secara sosial tidak diharapkan
melakukan pelanggaran dan yang kedua karena pelanggarannya itu sendiri. Kriminologi yang ada saat itu
adalah kriminologi laki-laki yang melihat masalah kejahatan dan pengendaliannya dalam pers-pektif
berfikir laki-laki (Segal, 1990) Oleh karena itu dipertanyakan kelayakan penelitian-penelitian tentang
perempuan pelanggar hukum dalam kriminologi feminisme, dan apakah teori kriminologi feminisme
merupakan keniscayaan (Smart, 1990). Dalam konsep dekonstruksi kejahatan yang merupakan salah
satu ciri aliran posmodern, kriminologi feminisme memperoleh pijakannya yaitu agar supaya krimi-
nologi melakukan dekonstruksi dalam dirinya sendiri dengan meninggalkan keberpihakan (bias) gender
dalam merumuskan kejahatan dan penyimpangan (Cain, 1990).
Sesungguhnya perspektif feminis kriminologi tidak hanya tunggal tetapi bhineka. Terdapat paling tidak
lima perspektif yang mempunyai landasan asumsi teoretis yang berbeda-beda, yaitu:
1. Feminisme Liberal
2. Feminisme Radikal
3. Feminisme Marxis
4. Feminisme Sosialis
5. Feminisme Posmodern
2.1. Feminisme Liberal
Feminisme liberal berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan berasal dari sosialisasi
peran berdasar gender. Peran sosial laki-laki (misal kompetitif dan agresif) menerima status sosial dan
kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan. Konsekuensinya feminisme liberal lebih memberi
tekanan kepada kesetaraan politik, sosial, hukum, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
Dalam kriminologi, feminis liberal memandang pelanggaran oleh perempuan sebagai fungsi
sosialisasi peren berdasarkan gender. Tingkat pelanggaran oleh perempuan lebih sedikit dibandingkan
laki-laki, karena sosialisasi memberikan kemungkinan kecil untuk melakukan pelanggaran
2.2. Feminisme Radikal
Feminisme radikal memandang patriarkhi (dominasi laki-laki), merupakan akar masalah dari
penindasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami diskrimisasi karena relasi sosial dan interaksi
sosial dibentuk oleh kekuasaan laki-laki dan hak-hak khusus laki-laki.
Dalam kriminologi, memfokuskan pada manifestasi patriarkhi kejahatan terhadap perempuan,
seperti KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi, dan mengakui bahwa pelanggaran oleh
perempuan akan diikuti dengan viktimisasi, oleh laki-laki.
5
2.3. Feminisme Marxis
Penindasan terhadap perempuan karena kedudukan subordinatnya dalam status kelas
masyarakat kapitalis. Cara produksi kapitalis membentuk hubungan kelas dan gender yang terutama
merugikan perempuan, karena perempuan menduduki kelas pekerja bukan kelas penguasa.
Dalam kriminologi, menjelaskan secara teoretis bahwa kedudukan subordinat dari perempuan
akan memaksa mereka melakukan kejahatan sebagai cara untuk membantu dirinya sendiri secara
ekonomi.
2.3. Feminisme Sosialis
Feminisme sosialis menggabungkan pespektif radikal dengan perspektif Marxis.
Penindasan terhadap perempuan merupakan hasil dari kecocokannya dengan jenis kelamin dan
ketidakadilan sosial berbasis jenis kelamin. Kelas dan jenis kelamin bekerja secara tandem dalam
struktur sosial, dan feminis sosialis mengundang penelitian tentang dengan cara-cara bagaimana
hubungan gender dibentuk oleh kelas dan gender dan sebaliknya.
Dalam kriminologi, penyebab kejahatan adalah konteks hubungan berbasis gender dan kelas
dalam sistem kekuasaan.
2.4. Feminisme Posmodern
Feminis Posmodern melandaskan diri pada perspektif yang lainnya dengan mempertanyakan
keberadaan setiap kebenaran, termasuk penindasan terhadap perempuan. Feminisme
Posmodern, menolak kategori yang tetap dan universal, dan mendukung kategori kebenaran jamak.
Kemudian mempelajari dampak dari wacana dan representasi simbolik terhadap klaim kebenaran.
Dalam kriminologi, feminisme menelaah secara tajam konsep kejahatan, keadilan, dan
penyimpangan, serta menantang kebenaran-kebenaran yang diterima dalam kriminologi.
Selain kelima perspektif umum di atas, terdapat pengkhususan perspektif seperti perspektif
perempuan kulit hitam dan perspektif kritis ras feminisme. Perspektif ini memberi perhatian
bagaimana bangsa-bangsa kulit putih melakukan disrkiminasi terhadap keturunan kulit hitam dan
minoritas ras lainnya. Ada juga perspektif feminisme lesbian yang mengaitkan penindasan
perempuan dengan heteroseksisme dan pengendalian perempuan oleh laki-laki, yang memandang
secara pesimistis terhadap laki-laki. Feminisme dunia ketiga memandang penindasan perempuan
merupakan fungsi eklpoitasi ekonomi terhdap perempuan di negara-negara sedang berkembang.
II. 3. Pengukuran kejahatan
Secara umum kriminologi posmodern berpendapat bahwa mendefinisikan kejahatan bukanlah hal
yang mudah karena akan selalu ada sisi bias dari pembuat definisi. Namun demikian untuk membuat
agar supaya kejahatan dapat dipahami secara komprehensif, perlu dilakukan pengukuran gejala
kejahatan sebagai gejala sosial secara lebih baik. Dalam usaha mendefinisikan kejahatan, Hagan
membuat alat ukur kejahatan yang disebutnya sebagai piramida kejahatan. Melalui piramida
tersebut akan dapat dipahami kejahatan yang dilihat melalui alat tersebut. Bagi Hagan, kejahatan
bukan merupakan variabel yang tetap (konstata), tetapi merupakan variabel tidak tetap (continues).
Kejahatan bervariasi bentuknya, ada yang berbentuk pelanggaran ringan seperti pelanggaran
ketertiban umum dalam bentuk mabok di depan publik sampai dengan pelanggaran berat seperti
terorisme dan pembunuhan masal. Hagan mendefinisikan kejahatan sebagai suatu jenis
penyimpangan dari berbagai bentuk norma sosial yang pada akhirnya akan dirumuskan dalam
6
hukum pidana (Hagan, 1985: 49). Dalam definisi tersebut perbedaan keseriusan kejahatan
tergantung pada tiga dimensi yang masing-masing mempunyai rentang dari peringkat rendah/ringan
hingga peringkat tinggi/berat. Yang pertama adalah agreement about the norm atau derajat
konsensus atau persetujuan, yaitu derajat tindakan yang oleh masyarakat akan diterima sebagai
benar atau salah. Hagan membuat kategori peringkat konsensus atau persetujuan tersebut mulai
dari yang terrendah tidak jelas atau tidak peduli, tidak sepakat, hingga sangat setuju sebagai
salah (Lanier, Henry, 2004: 28-29). Dimensi kedua adalah severity of societal response yaitu
keseriusan respon masyarakat yang tercantum dalam hukum. Respon sosial ini mulai dari
pengabaian, pemberian peringatan, hingga denda, penghukuman penjara, bahkan hukuman mati.
Menurut Hagan, semakin serius ancaman hukuman yang dirumuskan, semakin luas dukungan
terhadap sanksi tersebut, dan semakin serius penilaian masyarakat terhadap tindakan tersebut
(Lanier, Henry, 2004: 29). Dimensi ketiga adalah evaluation of social harm yang dirumuskan Hagan
sebagai keseriusan relatif dari kejahatan berdasarkan akibat yang dihasilkannya. Ada pelanggaran
hukum yang dampaknya hanya diderita pelanggar, seperti penyalahgunaan narokita, berjudi,
pelacuran dan lain-lain perilaku menyimpang. Ada pula pelanggaran hukum yang merugikan orang
lain baik dalam jumlah sedikit atau hanya satu dua orang, hingga pelanggaran hukum yang
merugikan banyak orang seperti kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi yang menjual
produk yang membahayakan kesehatan orang atau bahkan mematikan orang. Hagan kemudian
meragakan tiga dimensi tersebut menjadi piramida kejahatan (Lanier, Henry, 2004: 32).
Lenier dan Henry mengkritik bahwa piramida Hagan mempunyai beberapa kelemahan yaitu
menganggap tiga dimensi pengukuran kejahatan yang dibuat Hagan belum memadai atau tidak
lengkap. Kelemahan piramida Hagan menurut Lanier dan Henry karena mengabaikan kesadaran
publik tentang masalah realisasi kejahatan, yaitu adanya korban. Untuk menambal kelemahan
piramida Hagan, maka Lanier dan Henry mendisain ulang piramida tersebut menjadi piramida
ganda, yang kemudian disebut sebagai prisma. Lanier dan Henry menambahkan piramida terbalik di
bawah piramida Hagan. Puncak piramida mencerminkan kejahatan yang sangat tampak yang
biasanya dilakukan oleh kelompok yang lemah di muka publik. Misalnya perampokan, pencurian,
pencurian ranmor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, pembakaran. Pada bagian bawah, pada
piramida yang ditambahkan, mencerminkan kejahatan yang relatif tersembunyi. Ini meliputi
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang punya kuasa, misal pelanggaran yang
dilakukan oleh birokrat, korporasi, dan organisasi, maupun kejahatan-kejahatan dalam rangka
pekerjaannya, seperti penipuan, penggelapan, date rape, pelecehan seksual, KDRT, seksisme,
rasisme, ageisme, kejahatan kebencian. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang lemah
maupun yang kuasa hanya tampak setengah melalui prisma kejahatan. Disebut prisma bukan hanya
karena bentuknya tetapi juga dapat dipergunakan untuk menganalisa spektrum dimensi yang
membentuk kejahatan.
Penjelasan prisma tersebut meliputi kesepakatan sosial, rentang kesepakatan sosial dimulai dari
puncak prisma. Posisi a, mencerminkan kesepakatan umum; c. sedang; e. apatis atau tidak peduli
pada bagian prisma yang terlebar. Separoh prisma bagian bawah mencerminkan rentang
ketidaksepakatan sedang (i) hingga sangat tidak sepakat atau konflik ekstrim (l) pada dasar prisma.
7
II.4. Hate Crime.
Hate Crime adalah salah satu bentuk perluasan jangkauan definisi kejahatan. Secara definisi ia
merupakan bentuk penyerangan secara fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang karena rasa kebencian terhadap
pihak yang diserang. Pihak yang diserang atau korban tidak melakukan tindakan apapun yang dapat
membuat siapapun akan melakukan pembalasan. Hanya karena ia dibenci oleh pihak lain, yang
biasanya adalah pihak yang fanatik dengan identitas diri kelompoknya, maka korban akan diserang.
Contoh klasik hate crime adalah pemusnahan terhadap bangsa Yahudi yang dilakukan oleh Nazi,
penyerangan terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat oleh kelompok Klu Klux Klan.
II. 5. Chatastropic Criminology
Tema chatastropic criminology juga merupakan usaha untuk memperluas jangkauan penelitian
kriminologi malalui perluasan terhadap pengertian kejahatan. Secara umum chatastropic
criminology prihatin terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang menghasilkan bencana kemanusiaan,
yaitu terorisme dan genosida. Dalam review terhadap jurnal-jurnal penelitian kriminologi, perhatian
terhadap masalah terorisme dan genosida agak terlambat karena para ahli kriminologi posmodern
lebih memperhatikan persoalan perubahan struktur sosial daripada membahas bentuk-bentuk
kejahatan. Oleh karena itu, Yacoubian (2006) yang memperkenalkan konsep chatastropic
criminology menghimbau agar para kriminolog banyak melakukan penelitian terhadap masalah
bencana kemanusiaan tersebut.
II. 6. Topological representation of criminal event
Tema ini merupakan usaha untuk memvisualisasi peristiwa kejahatan berdasarkan lima dimensi
sehingga diharapkan dapat dirumuskan teori yang lebih komprehensif selaras dengan kompleksitas
masalah kejahatan. Menurut Verma dan Lodha (2002), dengan mempergunakan pendekatan
matematikal menganalisa lima dimensi kejahatan secara terpisah maupun gabungan sekaligus yang
meliputi peristiwa kejahatan yang meliputi hukum, pelaku, target dan/atau korban, tempat dan
waktu kejadian. Kelima komponen tersebut merupakan keadaan yang harus ada. Tanpa salah satu
komponen, tidak akan diperhitungkan sebagai peristiwa kejahatan. Melalui visualisasi tersebut
diharapkan dapat diperoleh pemahaman distribusi kejahatan dan cara pengendaliannya.
III. Teori-teori kriminologi Posmodern
Teori-teori yang dihasilkan oleh posmodern antara lain adalah:
1. Teori integratif
2. Teori chaos
3. Teori konstitutif
4. Power control theory
8
III. 1. Teori integratif
Teori Integrasi berarti menggabungkan dua atau lebih teori yang sudah ada, diseleksi berdasarkan
persamaannya, menjadi satu model teori yang dirumuskan ulang dan mempunyai nilai keunggulan
penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan masing-masing unsur teori asalnya (Farnworth 1989:
95) [Lenier, Henry, 2004: hlm. 342]. Kecenderungan mengintegrasikan beberapa teori dalam kriminologi
dimulai pada tahun 1979 berdasarkan unsur-unsur terbaik dari teori-teori yang digabung (Johnson,
1979; Elliot et.al. 1985)[Lenier, Henry, 2004: hlm. 342]. Setiap teori hanya benar menurut perspektifnya.
Untuk memahami kejahatan memerlukan penjelasan komprehensif. Teori-teori kriminologi yang amat
banyak dan bervariasi sudut pandang dan pendekatannya, dapat digabungkan satu sama lain untuk
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif (Barak, 2002). Kecenderungan penggabungan teori-
teori kriminologi juga didorong oleh keterbatasan sifat aplikatif dari masing-masing teori. Penggabungan
teori yang dilakukan dalam kriminologi tidak hanya terbatas di dalam satu perspektif, satu disiplin (ilmu
sosial), tetapi juga menjadi lintas disiplin bahkan multi disiplin. Daya tarik dalam teori gabungan adalah
membebaskan orang dari jerat perspektif, dan membuat teori gabungan sebagai bingkai kreatif
pluralitas pengetahuan (Barak 2002).
esungguhnya teori integratif tidak hanya dilakukan oleh pemikiran posmodern tetapi juga oleh
pemikiran modern. Menurut Barak ciri dari teori integratif posmodern tidak terletak pada teorinya
sendiri tetapi pada pengetahuan yang diperoleh. Posmodern tidak mencari hubungan sebab-akibat
dalam satu disipli atau antar disiplin, posmodern menghasilkan model-model penjelasan kejahatan dan
pengendaliannya yang menunjukkan hubungan sepanjang atau lintas pengetahuan interdisiplin yang
luas (Barak, 1998a).
Sebagai contoh, Vila (1994) dalam teori evolusi ekologi dalam karyanya "A General Paradigm for
Understanding Criminal Behavior: Extending Evolutionary Ecological Theory", konsisten dengan
semangat posmodern dalam menggabungkan teori sebab-musabab secara multidisiplin berdasarkan
pengetahuan. Vila melakukan integrasi berbagai teori menurut tingkat annalisanya seperti teori anonie,
teori pengendalian sosial, teori labeling dan teori belajar sosial yang berasal dari psikologi sosial, dan
pada tingkat yang lain ia menelaah menurut kurun waktu lintas disiplin, perubahan-perubahan yang
berasal dari perilaku "akusisi sumber daya" dan "retensi sumberdaya" dari para aktor sosial semenjak
masa anak-anak hingga dewasa.Dengan kata lain, model sintesa ini tidak hanya mempunyai akar pada
evolusi ekologi interdisiplin, tetapi mempergunakan pendekatan orientasi-masalah daripada orientasi-
disiplin dalam mempelajari tingkah aku kejahatan (VIla, 1994:315).
Richard Hervey Brown (1989:1) berpendapat bahwa: "konflik-konflik yang terjadi di dalam kebudayaan
kita, yaitu antara perbendaharaan kata-kata dalam wacana ilmiah dengan wacana naratif, antara
positivisme dengan romantisisme, antara objektivisme dengan subyektivisme, dan antara sistem dengan
kehidupan-dunia, dapat disentasakan melalui kebenaran yang puitis yang memandang ilmu-ilmu sosial
dan masyarakat sebagai teks". Berdasarkan pandangan ini, bahasa bukanlah refleksi dunia maupun
pikiran. Sebaliknya, praktik sejarah sosial ketika makna dari kata-kata tidak diambil dari benda-benda
atau maksud-maksud, tetapi berasal dari tindakan orang yang secara sosial terkordinasi.
9
Sampson dan Laub (1993:18) dalam Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life,
dalam pengembangannya tentang pendekatan "batu pijakan" terhadap delinkuensi dan kejahatan dapat
ditemukan pada data naratif sejarah hidup dan di dalam rekonstruksi sosial kejahatan. Dalam
penjelasannya tentang kejahatan, mereka menekankan pada "peran pengendalian sosial informal yang
muncul dari peran timbal-balik dan struktur ikatan antar pribadi yang menghubungkan anggota-anggota
masyarkat satu sama lain dan dengan pranata-pranata sosial yang lebih luas seperti pekerjaan, keluarga
dan sekolah.
Arrigo (1995) berpendapat bahwa kunci dari integrasi posmodern adalah dalam produksi analisa yang
tidak bersifat total dan penilaian yang tidak bersifat global. Bentuk integrasi yang dihasilkan Arrigo tidak
"didasarkan pada asumsi untuk mengetahui kondisi-kondisi atau penyebab-penyebab kejahatan atau
kontroversi legal dengan menawarkan baik integrasi yang berdasarkan model homeostatisatau teori
khusus yang kaku (Arrigo, 1995:465). Sebaliknya, menurut Arrigo posmodern lebih memilih untuk
memikirkan sintesa untuk merujuk pada "fungsi-fungsi ralasional, posisional, provisional dalam
menafsirkan dan menafsirkan ulang, memvalidasi, dan mengakui wacana-wacana jamak dan
ekspresinya tentang konstruksi realitas dalam susunan-susunan sosial yang berbeda-beda." Oleh karena
itu, ia dapat membuat sintesa narasi yang secara konseptual kaya yang menggabungkan berbagai
pengetahuan yang berbeda-beda seperti psikoanalisa, semiotika, pos-strukturalis, dekonstruksionisme,
agen manusia, pembentukan peran, perubahan sosial, dan lain-lain.
Messerscmidt (1997) dalam Crime as Structured Action: Gender, Race, Class, and Crime in the Making
terlibat dalam konstruksionisme dasar yang meliputi tidak hanya melalui wacana, tetapi juga lebih
penting lagi, melalui cara-cara ketika orang-orang secara aktif mengkonstruksi identitas mereka sendiri,
maskulin feminin, dalam hubungannya dengan kejahatan dan ko nteks sosial yang khusus karena
mereka berbeda-beda menurut waktu dan situasi dan juga melalui kelas, ras, gender dsb.
Menurut Henry dan Milovanovic (1996:x), tipe-tipe analisa integratif tersebut melampaui argumen
posmodern tentang kejahatan dan merupakan produksi rekursif (berulang), aktivitas-aktivitas rutin yang
merupakan bagian atau paket wacana dan struktur khusus sejarah dan budaya yang telah mencapai
stabilitas relatif menurut waktu dan tempat. Analisa tersebut berakar secara material, dan
wacanatentang ketidaksetaraan struktural tersebut, sebagai contoh, "menjadi kordinasi tindakan sosial
dan "pelaku kejahatan" tidak lebih merupakan "inveaistor yang berlebihan" dalam akumulasi dan
ekspresi kekuasaan dan pengendalian." Sebagai contoh, Barak dan Henry (1999) dalam "An Integrative-
Constitutive Theory of Crime, Law, and Social Justice," melakukan pengujian terhadap ko-produksi
kejahatan dan konsumsi kejahatan serta ko-produksi kejahatan dan keasilan (baik pelau maupun
masyarakat). Teori tersebut "menghubungkan kajian kebudayaan dengan kajian kejahatan. Ini
merupakan teori yang memelihara pluralitas perbendaharaan kata yang melaluinya orang yang berbeda-
beda mengalami kekerasan maupun bekerjanya kekuasaan sistem peradilan pidana. Menurut Arrigo
(1999: 151) ini merupakan teori yang mengintegrasikan berbagai sudut pandang menjadi sudut pandang
yang lebih lengkap, lebih kuat tentang hukum, kejahatan dan penyimpangan. Pada akhirnya, kata Barak,
Flavin, and Leighton (2001), bentuk-bentuk sintesa tersebut merupakan usaha untuk membawa
interseksi kelas, ras, dan gender bersama-sama dengan dinamika pembentukan identitas sosial dan
komunikasi massa.
10
III.2. Teori chaos
Teori tentang ketidakteraturan (chaos) berasal dari bidang metereologi dan dikembangkan dalam
bidang matematika dan fisika dipergunakan oleh T.R. Young (1991) untuk menjelaskan gejala kejahatan.
Berbeda dari makna harafiah kata chaos yaitu ketidak-teraturan, teori ini bicara tentang keteraturan
dari sesuatu yang tampak seperti ketidakteraturan. Atau dengan kata lain, berbagai hal yang selama ini
dipandang sebagai ketidak-teraturan sesungguhnya mempunyai ciri keteraturan. Namun keteraturan
dalam ketidakteraturan tersebut tidak bersifat linear dalam arti tidak pernah terjadi pengulangan yang
persis sama dan tidak bersifat periodik. Menurut penemu dari teori chaos yaitu Edward Lorenz (1960)
perubahan kecil pada kondisi awal akan dapat mengubah tingkah laku secara drastis dalam jangka
panjang, seperti misalnya kepakan sayap kupu-kupu akan dapat mengakibatkan terjadinya tornado.
Dampak dari kepakan sayap kupu-kupu tersebut mengakibatkan percabangan dua (bifurcation) yang
menghasilkan gambar yang mirip dengan sayap kupu-kupu yang disebut sebagai dimensi fraktal atau
merupakan atraktor.
Dalam teori ketidakaturan kejahatan, Young mengasumsikan bahwa ilmuwan pos-modern tidak
mempunyai definisi yang ditawarkan untuk menjelaskan ketertiban dan ketidaktertiban. Bila pos-
modern merujuk pada ketertiban yang dipergunakan dalam hukum dasar, praktik pemolisian dan
penghukuman, pos-modern menuntut syarat kepekaan terhadap kepentingan manusia dan proses
politik ketika dirumuskannya dan ditegakkannya pengertian ketertiban tersebut. Ketertiban memang
perlu ditegakkan, demikian juga bentuk lain (bifurcation) dari ketertiban juga perlu dimasyarakatkan.
Proses kemanusiannya memerlukan campuran antara ketertiban dan ketidaktertiban, karena terdapat
kecondongan yang kuat untuk mengutamakan ketertiban ketika terjadi kericuhan. Anarki harus dilihat
sebagai hal yang biasa saja bila terjadi di antara kelompok yang sebanding dengan sumber daya yang
sebanding pula, tetapi kenyataannya kekuasaan dan hak-hak khusus telah meracuni proses sosial
tersebut (Young, 1998:1).
Konsep chaos adalah ketidakteraturan yang luar biasa, dan reaksi terhadapnya untuk melakukan lebih
banyak usaha untuk memulihkan keadaan, mengendalikannya, dan menghasilkan konformitas terhadap
struktur norma yang ada adalah pandangan konservatif. Chaos adalah kajian tentang ketertiban dan
ketidaktertiban. Ketidaktertiban adalah hal yang penting bagi berbagai bentuk kehidupan. Ketertiban
dapat menghasilkan kematian; dan ketertiban yang diutamakan dalam ilmu-ilmu modern adalah impian
kaum tiran. Oleh karena itu konsep chaos sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan perlunya
ketertiban, yang diperlukan adalah adanya percampuran yang serasi antara ketertiban dengan keadaan
manusia dan terhadap suasana kehidupan tempat kehidupan ini bergantung (Young, Ibid).
Teori chaos tentang kejahatan adalah teori radikal yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil
(perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya
yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan. Setiap bentuk kejahatan dan setiap kejahatan
mempunyai sejumlah faktor yang menyebabkannya mempunyai daya tarik (attractive) atas hasilnya.
Sejumlah faktor tersebut antara lain adalah ketidaksetaraan kelas, gender, rasial, dan etnisitas. Namun
demikian ketidaksetaraan tersebut merupakan ketidaksetaraan non-linear. Dalam pandangan teori
chaos, ada ditemukan ketidaksetaraan yang tidak mempunyai dampak terhadap kejahatan. Penerapan
11
pertanyaan kriminologi non-linear adalah bagaimana rasio yang ada antara mereka yang berada di
bawah dengan mereka yang ada di atas dalam piramida kekuasaan, kesejahteraan, dan kehormatan
sosial. Terkait dengan angka-angka Feigenbaum (bahwa percabangan dua terjadi dalam rate yang
konstan), non-linear ini bertanya tentang berapa banyak ketidaksetaraan bermanfaat dan berapa
banyak pula ia menghasilkan ketidakstabilan. Di samping ketidaksetaraan dan pemeliharaan
ketidaksetaraan terdapat interaksi yang halus yang mungkin melandasi dinamika kejahatan, yaitu
parameter-parameter psikologis seperti ke-inginan (desire), ketidaknyamanan (insecurity), status, dan
tuntutan palsu atas barang-barang baru yang didorong oleh iklan yang akan membuat orang-orang
berubah menjadi daya tarik (attractor) satu sama lain. Dan nilai-nilai keagamaan menghasilkan lebih
banyak kejahatan; kejahatan terhadap perempuan, kejahatan terhadap suku terasing, dan terhadap
anak-anak. Kejahatan white-collar misalnya, besaran perbedaan antara keinginan dan kesejahteraan,
status dan kekuasaan di satu pihak dan perubahan dalam kesempatan memperoleh penghasilan,
penghargaan/pengakuan, dan pemenuhannya di lain pihak, merupakan faktor yang melatarbelakangi
kejahatan tersebut. Faktor penyebab bagi timbulnya kejahatan, dengan demikian, akan memberikan
pemahaman baru tentang kesalahan pidana. Bagi teori chaos, faktor penyebab merupakan hal yang
relatif tergantung pada skala analisa dan wilayah diagram percabangan dua (bifurcation), dan kesalahan
dapat bersifat fraktional / kecil saja (Young, 1998: 2).
III. 3. Teori Konstitutif
Pemikiran constitutive criminology yang mencoba meng-gabungkan pemikiran empirisme modern
dengan tetap mem-berikan kritik terhadapnya serta mengembangkan pemikiran pos-modern dengan
meninggalkan konsep dekonstruksionisme yang merupakan ciri pos-modern. Henry dan Milovanovic
mengemukakan teori constitutive criminology yang diakuinya sebagai pemikiran kriminologi kritis yang
matang. Pemikiran kriminologi konstitutif dipengaruhi oleh berbagai teori sosial kritis seperti interaksi-
simbolik, konstruksionisme sosial, fenomenologi, etnometodologi, struktural Marxisme, pos-
strukturalisme, teori strukturasi, dan semiotik (Henry dan Milovanovic, 2000:268). Menurut mereka,
dalam perkembangan pemikiran kriminologi konflik pendekatan yang dipergunakan adalah menolak
teori kriminologi yang mereduksi kejahatan sebagai semata-mata sebagai hasil dari konteks mikro dan
makro. Memahami kejahatan harus mempertimbangkannya sebagai hasil akhir dari wacana (discourse)
yang dilakukan oleh manusia dalam mempertahankan ideologi bahwa kejahatan adalah realitas yang
konkrit.
Berbeda dengan pemikiran pos-modern yang bersikap skeptis terhadap ilmu-ilmu sosial dan humaniora,
kriminologi konstitutif justru menyetujui penggunaan ilmu sosial dan humaniora dalam analisanya.
Pemikiran pos-modern dalam hal ini berpendapat bahwa tidak ada hak khusus dalam ilmu
pengetahuan. Setiap orang adalah pakar (Henry, Milovanovic, 1996:3). Meskipun demikian kriminologi
konstitutif sependapat dengan pemikiran pos-modern yang mengkritik empirisme ilmu sosial dalam
pemikiran modern, tetapi tidak menafikannya. Apabila pemikiran pos-modern mengedepankan de-
konstruksi, maka kriminologi konstitutif lebih mengedepankan rekonstruksi dan redireksi. Bagi
kriminologi konstitutif, dekonstruksi dan rekonstruksi adalah komponen pendamping yang penting bagi
pembentukan suatu dunia yang kurang bersifat merugikan, yaitu dunia yang dapat diperbaiki, terbuka
12
bagi perubahan, mengakomodasi munculkan bentuk-bentuk sosial yang memiliki raga dan inti (Henry,
Milovanovic, 1996: ix).
Kriminologi konstitutif mempromosikan bahwa mahluk manusia bertanggung jawab secara aktif bagi
pembentukan dunia bersama-sama dengan yang lain. Pembentukan tersebut dilakukan dengan
menstransformasi keadaan sekitarnya melalui interaksi dengan yang lain, paling tidak melalui wacana
Melalui bahasa dan representasi simbolik mereka menengarai perbedaan-perbedaan, mengkonstruksi
kategori-kategori, dan memiliki andil bersama suatu kepercayaan terhadap realitas yang dikonstruksi
sebagai ketertiban, bila tidak akan terjadi kekacauan. Konstruksi realitas sosial inilah yang harus dituju
oleh makhluk manusia (Ibid).
Dalam proses konstruksi sosial tentang kategori-kategori ketertiban dan realitas yang tidak saling
berhubungan, mahluk manusia tidak hanya sebagai pembentuk tetapi juga dibentuk olehnya. Mereka
adalah pembentuk pendamping dan hasil samping dari mereka sendiri bersama-sama dengan lain-lain
agen sosial. Makhluk manusia diberi saluran dan berubah, mempunyai kemampuan dan dibatasi
sepanjang masa dan proses pembentukan yang terus-menerus (Ibid).
Mengenai kejahatan, kriminologi konstitutif mengar-tikannya sebagai suatu ekspresi energi untuk
membuat suatu perbedaan dari yang lain, dikeluarkan oleh yang lain yang secara seketika membuat
pihak yang lemah membuat dirinya menjadi berbeda. Kejahatan adalah kekuasaan untuk meng-abaikan
yang lain, dan ini merupakan produksi yang berulang-ulang, secara historis, merupakan wacana budaya
yang khusus yang sudah mencapai tingkat kestabilan relatif. Karena kejahatan berakar secara
materialistik, wacana tentang keja-hatan menjadi koordinat tindakan sosial yang merupakan titik
tempat pelaku-pelaku kejahatan tidak lebih sekedar merupakan investor yang berlebihan dalam
akumulasi ekspresi kekuasaan dan pengendalian (Henry, Milovanovic, 1996: x).
Henry dan Milovanovic sebagai pelopor kriminologi konstitutif berpendapat bahwa kejahatan yang
merupakan hasil bersama tersebut muncul bila para agen (manusia) bertindak di luar pola kejahatan,
apabila yang satu ingin mengendalikan tingkah laku jahat, dan apabila yang lain lagi mencoba untuk
menelitinya, melakukan telaah filosofis, dan menjelaskanya. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa
mengurangi kejahatan akan menghasilkan pengurangan investasi manusia dalam ideologi produksi
kejahatan. Refleksi rekonseptualisasi kejahat-an tersebut membutuhkan pengembangan wacana peng-
gantinya, daripada menentangnya, yaitu suatu wacana peacemaking dan bukan wacana konflik (Henry,
Milovanovic, 1991: 293-316). Konsep-konsep constitutive criminology, post-structuralis criminology, dan
integrative criminology tampaknya oleh Milovanovic dipergunakan sebagai istilah yang bergantian.
Bahkan salah satu tokoh kriminologi pos-modern juga menawarkan model analisa kejahatan yang tidak
membatasi diri pada salah satu aliran pemikiran maupun cabang ilmu, yang ia sebut sebagai integrative
criminology (Lihat Barak, 2002).
Milovanovic (1997) dalam usahanya menjelaskan kriminologi pos-modern yang bukan barang lama tapi
dengan baju baru, memberikan uraian perbedaan antara kriminologi modern dengan kriminologi pos-
modern. Kriminologi modern yang dimaksud oleh Milovanovic adalah teori-teori kriminologi aliran
pemikiran positivis dan interaksionis. Menurut pendapat Milovanovic, adalah tidak benar bahwa orang
13
berpendapat kriminologi pos-modern adalah kriminologi modern yang diberi baju baru. Kriminologi pos-
modern sungguh-sungguh merupakan pemikiran yang secara radikal mempergunakan konsep-konsep
baru. Apabila pemikiran kriminologi modern berasal dari era pencerahan, yaitu era pembebasan ilmu
sosial sebagai akibat kemakmuran kapitalis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang asbstrak dari
setiap orang, pemikiran pos-modern berdasarkan pamahaman sensitif terhadap karya-kraya klasik mulai
dari Marx, Weber, Durkheim, Freud hingga pemikiran kritis aliran Frankfurt, dan asal muasal pemikiran
itu berasal dari Prancis (Milovanovic, 1995:2). Selanjutnya ia mengatakan bahwa teori-teori pos-modern
membahas tentang teori chaos, teori Godel, teori katastrof (bencana alam), mekanika quantum, dan
teori topologi (Ibid). Tampak bahwa teori-teori pos-modern banyak menyerap teori ilmu alam, dan
bahkan dalam penelitiannya juga mempromosikan penggunaan metode penelitian alam.
Menurut Pettit (2002) kriminologi konstitutif merupakan usaha untuk membangun perspektif yang baru
dalam teori kriminologi. Perspektif ini berlandaskan pada analisa pos-modern. Kriminologi konstitutif
sebagai pencarian ilmiah merupakan sintesa dari berbagai macam sintesa radikalisme yang meliputi:
interaksionisme simbolik, dekonstruksifisme, sosiologi penomenologi, dan filsafat bahasa. Lebih jauh
perspektif ini terutama memberi perhatian pada penafsiran dan penafsiran ulang terhadap realitas.
Dengan berlandaskan pada pandangan pos-modern, kriminologi konstitutif berpendapat bahwa melalui
pandangan ini dimungkinkan untuk merekon-struksi kebenaran (truth). Terkait dengan kejahatan,
menurut kriminologi konstitutif, kejahatan dan pengendaliannya harus ditelaah dalam rangka totalitas
konteks semua kebudayaan yang ada. Melalui pandangan ini perlu memperluas konsep kerugian
termasuk semua kekuasaan yang bersifat menyerang mahluk manusia, tidak semata-mata dibatasi oleh
pandangan sempit tentang sifat memaksa dari kejahatan jalanan. Berdasarkan teori ini, tindakan kaum
bisnis dan politisi bila mereka merecoki otonomi yang lain akan dapat dikategorikan dalam isu
tindakan yang merugikan. Dengan demikian kejahatan dibentuk melalui serangkaian proses interaksi
sosial (Pettit, 2002: 84).
Teori kriminologi konstitutif, menurut Pettit selanjutnya, memberikan landasan untuk melakukan
evaluasi ulang terhadap kepercayaan umum yang ada sekarang ini tentang pelaku pelangaran seksual,
tuna wisma, kasus-kasus yang serius, agen-agen hukum, dan persepsi tentang keburukan. Tipe-tipe
pelanggaran tersebut merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang kompleks, dan pandangan
tradisional yang tertuang dalam penafsiran hukum tidak sesuai dengan realitas sosial. Dalam hal ini
hukum lebih bertindak mengkolonisasi warganya daripada meniadakan kerugian (Pettit, 2002: 84-85).
III.4. Power Control Theory
Teori ini merupakan teori yang mencerminkan perspektif gender tentang perbedaan kenakalan yang
dilakukan oleh anaka-anak laki-laki dibandingkan anak-anak perempuan. Teori yang dirumuskan oleh
Hagan ini bersamsumsi bahwa perbedaan gender dalam kejahatan adalah fungsi kekuasaan ekonomi
dan pengendalian oleh orang-tua terhadap anak. Dalam penjelasan teoretisnya dikatakan bahwa anak-
anak perempuan lebih ketat dikendalikan dibandingkan anak laki-laki dalam keluarga yang didominasi
oleh tradisi dominasi laki-laki, sedangkanpada keluarga yang egaliter anak-anak perempuan dikendalikan
secara sama dengan anak-anak laki-laki. Menurut Hagan, kenakalan dan kejahatan merupakan fungsi
dari dua faktor: 1) Posisi kelas (power); dan fungsi-fungsi keluarga (control).
14
Hubungan antara dua variabel tersebut adalah bahwa dalm keluarga, orang-tua mereproduksi hubungan
kekuasaan yang diperoleh di tempat kerja. Suatu posisi yang dominan di tempat kerja akan diwujudkan
dalam bentuk pengendalian di keluarga. Sebagai akibatnya, pengalaman pekerjaan orang-tua dan posisi
kelas mempengaruhi kriminalitas pada anak-anaknya.
Pada keluarga paternalistik, ayah dianggap mempunyai peran tradisional sebagai pencari nafkah,
sedangkan ibunya cenderung mempunyai peran yang tidak penting dalam mencari nafkah atau tetap di
rumah untuk mengawasi urusan-urusan rumah tangga. Ibu-ibu mengendalikan tingkah laku anak-anak
perempuannya dan memberikan kebebd=asan kepada anak laki-lakinya. Ibu-ibu menyiapkan anak-anak
perempuannya untuk menjaga tradisi mengurus rumah tangga. Anak-anak laki-laki bebas untuk
menyimpang karena bebas dari pengendalian ibunya dan juga mempunyai akses yang lebih besar untuk
melakukan tingkah laku orang dewasa yang sah (kerja paroh waktu atau bepergian). Sebaliknya, tanpa
pelepasan tingkah laku sah ini, anak-anak perempuan yang tidak bahagia atau tidak merasa puas dengan
statusnya didorong untuk melakukan tingkah laku pelarian yang berresiko, termasuk tingkah laku
keputusasaan seperti lari dari rumah dan berusaha bunuh diri.
Pada keluarga egaliter, yaitu ketika suami dan isteri mempunyai posisi yang serupa, mereka berbagi
posisi kekuasaan di rumah dan di termpat kerja, anak-anak perempuan memperoleh kebebasan yang
mencerminkan berkurangnya pengendalian keluarga.
IV. Pengendalian kejahatan.
Salah satu ciri utama dari kriminologi posmodern adalah berambisi menyelesaikan masalah kejahatan
yang tidak menimbulkan masalah yang lain. Selain itu, kriminologi posmodern juga berusaha agar
supaya kriminologi mempunyai manfaat praktis bagi masyarakat, yang dalam hal ini menyelesaikan
masalah kejahatan tanpa menimbulkan masalah baru.
Dalam konteks pengendalian kejahatan di samping secara konsekuen dilakukan oleh kriminologi realis
berupa rekomendasi terhadap polisi lokal untuk melakan perlindungan terhadap kelompok-kelompok
yang rentan menjadi korban kejahatan di wilayah itu, juga dihasilkan rekomendasi yangdikenal sebagai
peacemaking criminology dan restorative justice.
IV. 1. Peacemaking criminology
Dasar pemikiran dari kriminologi perdamaian adalah bahwa kekerasan dan ketakutan terhadapnya dan
derita darinya adalah berbahaya. Ia berasal dari orang-orang yang berdasarkan agenda kebebasannya
dan tujuannya, mengejar sesuatu dengan tanpa memperhitungkan dampaknya bagi orang-orang lain.
Sebaliknya, responsiveness adalah interaksi ketika agenda pribadi diubah secara terus-menerus dengan
mengakomodasi perasaan dan kebutuhan orang lain.
Pepinsky (2000) mengatakan bahwa: Perdamaian menggantikan kekerasan bilamana interaksi menjadi
responsif (Pepinsky, 1988, 1991). Ketika kekerasan dan ketakutan serta penderitaan darinya
membahayakan orang dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan dan agenda-agenda kebebasan
dirinya tanpa memandang apakah akan berdampak pada orang lain, responsiveness merupakan
15
interaksi ketika agenda-agenda pribadi para aktor berubah secara konstan, mengakomodasi perasaan-
perasaan dan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak lain. Responsiveness adalah bagaimana orang
bertindak dalam demokrasi partisipatoris, . . . yaitu cara membuat orang bertingkah laku beradab
daripada menghukum kriminalitas (Pepinsky dan Jesillow 1992 [1984]: 127-38).
Berbagai urusan akan menjadi lebih aman dan lebih jujur, apabila insentif pajak dan berbagai subsidi
diberikan untuk membantu bisnis yang dilakukan oleh pekerja/klien dan dioperasikan dan dimiliki secara
demokratis. Penjara menjadi tempat yang aman apabila dikelola secara demokratis. Merespon
kejahatan dan kekerasan dilakukan dengan membangun keamanan, dengan menghimbau para korban
dan para pelaku memperoleh dukungan komunitas dalam menemukan cara mereka sendiri ke arah
komunitas yang aman, seperti VORPS (Victim Offender Reconciliation Programs).
Demokratisasi (partisipatoris) adalah jalan setapak menuju perdamaian. VORPS membangun keamanan
dengan cara menghimbau korban dan pelaku melalui bantuan komunitas menghasilkan cara sendiri
untuk menjamin kehidupan komunitas yang aman. Menurut Christie (1977) VORPS merupakan cara
menyelesaikan masalah oleh mereka sendiri. Usulan yang seirama misalnya abolisi, restorative justice.
Nama peacemaking criminology diberikan oleh Pepinsky bersama-sama dengan Quinney (1991) yang
berusaha mencari dasar-dasar yang mendorong orang untuk menghasilkan perdamaian sebagai
pengganti kekerasan.
IV. 2. Restorative Justice.
Secara definisi, restorative justice adalah usaha untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik kejahatan
secara informal yang dilakukan secara non formal oleh warga masyarakat sendiri. Tujuan utama dari
cara ini adalah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik agar supaya kembali seperti
keadaan seperti sebelum konflik. Cara penyelesaian konflik ini harus merupakan kesepakatan tulus dari
pihak-pihak yang berkonflik dan direstui oleh masyarakat. Sesungguhnya restorative justice diadopsi dari
cara bangsa-bangsa Timur di dalam menyelesaikan konflik secara adat dengan menerapkan hukum adat
yang ciri utamanya adalah mengupayakan perdamaian yang menghasilkan keadilan substantive. Dengan
demikian perlu disadari bahwa konsep restorative justice sesungguhnya adalah praktik hukum adat dari
bangsa-bangsa Timur.
Dalam perkembangan hukum di Barat, bangsa Barat tidak puas dengan hasil bekerjanya sistem hukum
mereka sendiri. Konflik perdata yang yang diselesaikan di pengadilan akan bermuara pada keputusan
kalah-menang, sedangkan konflik pidana bermuara pada keputusan benar-salah. Keputusan pengadilan
yang oleh Weber disebut sebagai keadilan prosedural telah kehilangan kemampuannya menghasilkan
keadilan subtantiv. Bahkan konflik antara para pihak kendatipun sudah ada keputusan pengadilan yang
bersifat tetap, masih berjalan terus sebab keadilan substantiv tidak dapat dipenuhi melalui sistem
hukum formal.
Dalam upaya mencari solusi hukum yang lebih baik, secara pelahan bangsa Barat meninggalkan doktrin
hukum yang kaku. Dimulai dari bidang perdata yang memperkenalkan penyelesaian yang
menguntungkan para pihak melalui arbitrase. Di bidang pidana pencarian keadilan substantiv dipicu
antara lain oleh cara bangsa Afrika Selatan yang ketika membebaskan diri dari politik apartheid, tidak
16
melakukan pembalsan dendam terhadap minoritas kulit putih. Alih-alih melakukan balas dendam
kebijakan otoritas baru warga asli Afrika berkulit hitam membuat kebijakan pembentukan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ruh dari KKR ini adalah pengakuan bersalah dan perdamaian bukan
dendam serta mengesampingkan unsur pidana dari para penguasa kulit putih sebelumnya. KKR pernah
juga diundangkan di Indonesia dalam rangka merspon pelanggaran berat HAM. Namun sayangnya
melalkui judicial review di Mahkamah Konstitusi undang-undang KKR tersebut dibatalkan. Pembatalan
tersebut lebih diwarnai oleh pemahaman hukum yang bersifat legalistik yang jauh dari realitas
bekerjanya masyarakat Timur.
Salah satu temuan penting bangsa Barat dalam menyelesaikan konflik pidana yang diharapkan
menghasilkan keadilan substantiv adalah restorative justice yaitu penyelesaian konflik pidana secara
non formal diserahkan kepada komunitas yang bersangkutan yang bertujuan untuk memulihkan
kerugian korban dan juga memulihkan hubungan para pihak dan direstui oleh masyarakat.
Sesungguhnya restorative justice adalah praktik hukum adat yang banyak dilakukan oleh suku-suku
bangsa pada masyarakat bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia. Oleh karena itu karena restorative
justice sesungguhnya merupakan filsafat hukum bangsa Timur (Oriental) maka kebijakan hukum
penerapan restorative justice seyogyanya sebagian besar diartikan sebagai revitalisasi hukum adat, bila
konflik terjadi di antara sesama pendudkung hukum adat yang sama. Revitaisasi ini memperoleh pijakan
yang kokoh yaitu UUD 1945 Amandemen ke empat, secara tegas mengakui eksistensi masyarakat
hukum adat.
V. Perkembangan mutakhir.
Pemikiran-pemikiran kriminologi terus berkembang, tidak hanya berakhir dengan pemikiran posmodern.
Termasuk dalam pemikiran mutakhir adalah perhatian dari para ahli kriminologi yang mengamati
adanya kriminalisasi terhadap budaya pop yang diwujudkan dalam seni pop seperti grafiti, budaya punk
yang mendorong dihasilkannya pemikiran kriminologi budaya. Dalam perkembangannya kriminologi
budaya menjadi suatu analisa yang terintegrasi antara analisa budaya dengan analisa kriminologi
terhadap cara-cara hidup yang merugikan. Bahkan dalam pemikiran ini, kejahatan dipandang sebagai
budaya (cara hidup). Namun tidak berarti bahwa kriminologi budaya membenarkan kejahatan. Yang
berbeda adalah dalam rekomendasi penyelesaian masalah, diwarnai oleh pemikiran posmodern yaitu
menyelesaikan masalah tanpa masalah yang dilakukan dengan cara menawarkan wacana pengganti
yaitu cara hidup yang tidak merugikan pihak lain. Sementara itu cara hidup yang "normal" bila ternyata
merugikan budaya lain, maka budaya tersebut juga dikategorikan sebagai kejahatan. Budaya "toko
swalayan" adalah budaya yang "normal". Namun dalam kenormalannya itu ternyata telah mematikan
warung-warung tradisional, dan itu adalah kejahatan.
Secara lebih khusus kriminologi budaya, menyoroti peran media massa yang seringkali membesar-
besarkan masalah kejahatan dan menjadikan kejahatan sebagai komoditas. Perhatian khusus terhadap
konstruksi kejahatan oleh media ini menghasilkan pemikiran newsmaking kriminology.
17
Referensi
Amanda Burgess-Proctor. Intersection of Race, Class, Gender, and Crime: Future Directions for Feminist
Criminology. Feminist Criminology 2006, 1: pp.27-47 http://fcx.sagepub.com/content/1/1/27
Dragan Milovanovic (1997), Dueling paradigms: Modernist v. Postmodernist thought. Revised version from
Humanity and Society, 19(1): 1-22, 1995; and revised in Dragan Milovanovic, Postmodern
Criminology. New York: Garland Publishing.
Hal Pepinsky, A Criminologist's Quest For Peace, Criminal Justice Policy Review, 11, 2 (December 2000)
Jeff Ferrell, Crime And Culture, Dalam C. Hale, K. Hayward, A. Wahidin, E. Wincup. Criminology. Oxford:
Oxford Univ. Press, 2005
John Hagan, John Simpson, A.R. Gillis (1987), "Class in the Household: A Power-Control Theory of Gener and the
Delinquency." American Journal of Sociology. Vol . 92, No. 4, hlm. 788-816.
John Hagan. The Disreputable Pleasures. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1977.
Lea, J., dan J. Young (1984), What is to be Done about Law and Order? Harmoundsworth: Penguin.
Mark M. Lanier & Stuart Henry. Essential Criminology, 2
nd
Edition. Oxford: Westview Press, 2004
Rock, P. (1992), The Criminology that Came in Out of the Cold, dalam J. Lowman, and B.D. MacLean. Realist
Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s. Toronto: University of Toronto, hlm. 139-156.
hal. ix-xii.
Verma, Arvin & S.K. Lodha (2002), "A Topological Representation of the Criminal Event." Western
Criminology Review 3 (2) [Online]. Available at http://wwcr. sonoma.edu/v3n2/verma.html.
Yacoubian, G.S. (2006), "Genocide, Terrorism and Conceptualization of Catastrophic Criminology", War
Crime, Genocide & Crime Against Humanity , Volume 2, pp. 65-85.
Young, J. (1992), Realist Research as a Basis for Local Criminal Justice Policy, dalam J. Lowman, and B.D.
MacLean. Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s. Toronto: University of
Toronto, hlm. 32-72.
You might also like
- KriminologiDocument118 pagesKriminologifirman_bharats100% (7)
- PERKEMBANGAN KRIMINOLOGIDocument6 pagesPERKEMBANGAN KRIMINOLOGISakhiya SovaNo ratings yet
- Kriminologi KontemporerDocument15 pagesKriminologi KontemporerSyahlan Aidil100% (1)
- Kriminologi Stik PtikDocument81 pagesKriminologi Stik PtikStill WhyNo ratings yet
- Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski TugasDocument11 pagesKonsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski TugasZulkifliThamrinNo ratings yet
- HukumAntropologiDocument9 pagesHukumAntropologiArifNo ratings yet
- Naskah Akademik HukumDocument4 pagesNaskah Akademik HukumLaurent Arnelia80% (5)
- Ringkasan BukuDocument3 pagesRingkasan BukuSherry SherLock Graycells100% (5)
- Definisi, Pengertian Dan Karakteristik Sosiologi HukumDocument3 pagesDefinisi, Pengertian Dan Karakteristik Sosiologi HukumDiwan Eztheim100% (1)
- UTS Sosiologi HukumDocument1 pageUTS Sosiologi HukumAfif FaridNo ratings yet
- Politik Hukum AgrariaDocument24 pagesPolitik Hukum Agrariayudiant63% (8)
- Hukum ViktimologiDocument10 pagesHukum ViktimologiDaniNo ratings yet
- Makalah Realisme HukumDocument15 pagesMakalah Realisme HukumZiko Erlangga71% (7)
- Makalah KriminologiDocument10 pagesMakalah Kriminologierwin januarNo ratings yet
- KEMISKINANDocument10 pagesKEMISKINANAde GunawansNo ratings yet
- Penelitian Hukum NormatifDocument7 pagesPenelitian Hukum NormatifM. Tajuddin N. SNo ratings yet
- Politik Hukum di IndonesiaDocument5 pagesPolitik Hukum di IndonesiaDOLAN DEWENo ratings yet
- Perbandingan Hukum Pidana Antara Indonesia Dengan Korea SelatanDocument33 pagesPerbandingan Hukum Pidana Antara Indonesia Dengan Korea SelatanLili60% (5)
- Prof. Muhammad Mustofa - Kriminologi Untuk Kesejahteraan Rakyat IndonesiaDocument35 pagesProf. Muhammad Mustofa - Kriminologi Untuk Kesejahteraan Rakyat IndonesiaTimothy Nugroho100% (2)
- Ruang Lingkup Hukum PenitensierDocument8 pagesRuang Lingkup Hukum PenitensierRosyid KurniawanNo ratings yet
- Jessie Bernard2Document18 pagesJessie Bernard2DimasGustiPradistaNo ratings yet
- Tindak Pidana TERORISMEDocument31 pagesTindak Pidana TERORISMEvicky saputra50% (2)
- Analisis KasusDocument4 pagesAnalisis KasusMochamad Bayu KresnaNo ratings yet
- Bahan Ajar Hukum KepariwisataanDocument23 pagesBahan Ajar Hukum KepariwisataanKinandara AnggaritaNo ratings yet
- Teori Hukum EsensiDocument117 pagesTeori Hukum EsensiAditya Sanjaya80% (5)
- FILHUM (Paradigmatik)Document8 pagesFILHUM (Paradigmatik)nindyafitriNo ratings yet
- Proposal Penelitian HukumDocument6 pagesProposal Penelitian HukumYanuar Dwi Anggara50% (2)
- TEORI ANOMIE DAN KORUPSIDocument7 pagesTEORI ANOMIE DAN KORUPSIAdityaPutraNo ratings yet
- Peran Psikologi Forensik Dalam Proses Hukum Di IndonesiaDocument28 pagesPeran Psikologi Forensik Dalam Proses Hukum Di IndonesiaRona Patricia Sibarani100% (1)
- Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori - Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ModernDocument29 pagesKajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori - Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ModernRisca ApriyanaNo ratings yet
- Sistem Peradilan Pidana ModelDocument11 pagesSistem Peradilan Pidana ModelRicky TrisatriaNo ratings yet
- Filsafat HukumDocument18 pagesFilsafat HukumNofry HardiNo ratings yet
- Teori Hukum Program s2Document13 pagesTeori Hukum Program s2Rafki RahmatNo ratings yet
- SOSIOLOGI HUKUMDocument10 pagesSOSIOLOGI HUKUMAnonymous VecWzPH33% (3)
- Panduan Wawancara PSKDocument2 pagesPanduan Wawancara PSKAulia100% (1)
- Makalah Diklat Kemahiran HukumDocument15 pagesMakalah Diklat Kemahiran HukumNanda SuratnoNo ratings yet
- Hubungan AntropologiDocument12 pagesHubungan AntropologiUsq Al Qalam KendariNo ratings yet
- Restorative JusticeDocument26 pagesRestorative JusticeJefry Fernando SinagaNo ratings yet
- PsikologiForensikDocument9 pagesPsikologiForensikRicky ImranNo ratings yet
- Teori Hukum Dan Sosiologi HukumDocument8 pagesTeori Hukum Dan Sosiologi HukumMUHAMMAD NUR UDPANo ratings yet
- Metode Pendekatan Sosiologi HukumDocument30 pagesMetode Pendekatan Sosiologi Hukumtakuya_eek100% (5)
- UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAKDocument20 pagesUPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAKendarNo ratings yet
- Review Singkat Teori Dramaturgi, Erving GoffmanDocument8 pagesReview Singkat Teori Dramaturgi, Erving GoffmanPurnamaPrajnaNo ratings yet
- Laporan PengamatanDocument5 pagesLaporan PengamatanShodik100% (1)
- Resume Buku Argumentasi HukumDocument12 pagesResume Buku Argumentasi Hukumgabrieltheofani80% (5)
- TigaNilaiHukumDocument5 pagesTigaNilaiHukumAdi Tamrin0% (1)
- Pendekatan Sosiologi Terhadap HukumDocument8 pagesPendekatan Sosiologi Terhadap HukumDellas Ka'u100% (1)
- Analisis Kasus PercobaanDocument11 pagesAnalisis Kasus PercobaanEko Budi100% (1)
- Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi HukumDocument9 pagesKarakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi HukumAndri HermawanNo ratings yet
- Perbandingan Asas Legalitas KUHP Indonesia dan FilipinaDocument24 pagesPerbandingan Asas Legalitas KUHP Indonesia dan FilipinaAska Halid100% (1)
- Ujian Mid Metopel Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten KlatenDocument15 pagesUjian Mid Metopel Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa Di Kabupaten KlatenDeny Aulia RidhaNo ratings yet
- Bab 7Document4 pagesBab 7Jafar Al FaudziNo ratings yet
- SOAL Kriminologi 2021 UASDocument6 pagesSOAL Kriminologi 2021 UASmuhammad dzikra azidanNo ratings yet
- Pencemaran Nama BaikDocument44 pagesPencemaran Nama BaikalrahmabkoNo ratings yet
- Aliran Kriminologi - NotaDocument12 pagesAliran Kriminologi - NotaFaiznor PSNo ratings yet
- Aliran KriminologiDocument9 pagesAliran KriminologiRija akhmad fauzyNo ratings yet
- Kriminologi Dan ViktimologiDocument9 pagesKriminologi Dan ViktimologiAdrian Hartanto Darma Sanputra0% (1)
- Kriminologi 2Document23 pagesKriminologi 2Sendi Viola. LNo ratings yet
- Kel.5 KriminologiDocument5 pagesKel.5 KriminologiDestriana PPKNNo ratings yet
- Uts KriminologiDocument4 pagesUts KriminologiSou ChanelNo ratings yet
- Bentuk Kekerasan PacaranDocument1 pageBentuk Kekerasan PacaranAmal BahriNo ratings yet
- Tugas 1Document3 pagesTugas 1Amal BahriNo ratings yet
- Perkawinan Dibawah UmurDocument3 pagesPerkawinan Dibawah UmurAmal BahriNo ratings yet
- CV-Tri HartonoDocument2 pagesCV-Tri HartonoArya RagilNo ratings yet
- Latar Belakang Dan TeoriDocument3 pagesLatar Belakang Dan TeoriAmal BahriNo ratings yet
- Perilaku MenyimpangDocument1 pagePerilaku MenyimpangAmal BahriNo ratings yet
- Belahan Otak Dan Otak KiriDocument2 pagesBelahan Otak Dan Otak KiriAmal BahriNo ratings yet
- Belahan Otak Dan Otak KiriDocument2 pagesBelahan Otak Dan Otak KiriAmal BahriNo ratings yet